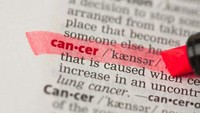Kemunculan deklarasi HAM internasional merupakan respons negara-negara di dunia atas berkecamuknya krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh peristiwa Perang Dunia I dan II. Jatuhnya banyak korban jiwa dan merosotnya nilai-nilai kemanusiaan akibat Perang Dunia I dan II menggerakkan kesadaran dunia internasional untuk melahirkan sebuah komitmen bersama untuk saling menghargai dan melindungi harkat dan martabat manusia.
Jauh sebelum PBB merilis deklarasi HAM internasional, konstitusi Republik Indonesia secara implisit telah mengakui hak dasar setiap manusia. Dalam Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945, terutama pasal 27 sampai 34 dengan gamblang termuat pasal-pasal yang menjamin hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama. Secara khusus, persoalan HAM diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, pada kenyataannya sampai saat ini bangsa Indonesia belum benar-benar lepas dari persoalan terkait pelanggaran HAM. Bahkan, bisa dibilang sejarah perjalanan bangsa Indonesia selalu tidak pernah lepas dari persoalan pelanggaran HAM. Di satu sisi, kita memiliki setumpuk persoalan terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu, mulai dari pelanggaran HAM berat pada kasus pembantaian massal anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia tahun 1965-1966, kasus kerusuhan 1998, serta banyak kasus pelanggaran HAM lainnya di masa lalu yang hingga hari ini belum menemui kejelasan.
Di sisi yang lain, kita juga menghadapi berbagai praktik pelanggaran HAM di era sekarang yang muncul akibat kebijakan pembangunan pemerintah yang cenderung liberalistik, pro pada kepentingan pemilik modal dan abai pada hak-hak dasar manusia. Seturut catatan Komisi Nasional untuk Tindak Kekerasan dan Orang Hilang (KontraS), pelanggaran HAM yang terjadi selama era Reformasi ini didominasi oleh kasus-kasus kekerasan yang diaktori oleh kelompok pemilik modal yang bersekutu dengan aparatur negara. Kebijakan pemerintah untuk mengakselerasikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi telah membuka lebar-lebar pintu masuk bagi para investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor.
Di lapangan, kepentingan para pemilik modal yang disponsori sepenuhnya oleh negara dan aparaturnya ini kerap tidak adaptif dengan kepentingan masyarakat lokal. Gesekan, bahkan benturan antara masyarakat lokal dan pemilik modal yang dilindungi negara pun acapkali tidak terhindarkan. Konflik agraria yang kerap berujung pada serampasan lahan dan penggusuran paksa yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan adalah hal yang lumrah dan nyaris menjadi sesuatu yang klise di negeri ini. Ironisnya, negara justru secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada pemilik modal, alih-alih masyarakat umum.
Dalam catatan KontraS, sepanjang 2018 terjadi setidaknya 488 kasus pelanggaran HAM yang dilatari oleh konflik antara pemilik modal dengan masyarakat lokal. Dari ratusan kasus tersebut, pihak yang paling banyak dilaporkan atas tindakan pelanggaran HAM ialah korporasi, kepolisian dan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan asumsi bahwa di lapangan, negara beserta aparatusnya justru kerap menjadi sponsor bagi tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sejumlah korporasi nakal.
Jika ditilik dalam perspektif sosial-politik yang lebih luas, persoalan terkait pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi dan negara sebagaimana masif terjadi beberapa tahun belakangan ini merupakan residu dari model pembangunan nasional yang mengadopsi paham developmentalisme. Pembangunan beraliran developmentalisme digagas oleh negara-negara maju (Barat) sebagai solusi bagi negara-negara dunia ketiga agar mampu mengakselerasikan pertumbuhan ekonominya pasca Perang Dunia II.
Developmentalisme bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik secara masif dan membuka lebar-lebar pintu investasi asing. Pembangunan infrastruktur fisik secara masif yang dibiayai investasi asing diyakini akan membuka lapangan pekerjaan dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang besar, meningkatkan konsumsi domestik dan diyakini mampu mengatrol pertumbuhan ekonomi.
Sebagai anak kandung sistem ekonomi kapitalisme, paham developmentalisme memiliki watak yang liberalistik-eksploitatif. Watak liberalistik itu mewujud ke dalam mekanisme ekonomi yang diserahkan sepenuhnya pada swasta berbasis persaingan bebas. Sedangkan watak eksploitatif itu terejawantahkan ke dalam praktik pengelolaan sumber daya alam yang abai pada kelestarian alam dan tidak ramah pada kepentingan masyarakat lokal. Konsekuensi dari penerapan model pembangunan bercorak developmentalistik ialah maraknya berbagai praktik pelanggaran HAM yang dilatari oleh persoalan terkait akses ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.
Di satu sisi, otoritas negara dalam mengurusi akses ekonomi dan mengelola sumber daya alam kian melemah, tergantikan dengan dominasi korporasi. Di saat yang sama, masyarakat lokal kerap harus berhadapan dengan korporasi yang mendapat endorsement dari pemerintah untuk menguasai akses ekonomi dan sumber daya alam dengan cara-cara yang abai pada nilai dan prinsip HAM. Kondisi yang demikian mirip seperti ramalan pemikir sosialis Karl Marx yang berujar bahwa pada di sistem kapitalisme negara tidak ubahnya seperti pelayan bagi kaum pemilik modal.
Revitalisasi
Dalam kondisi yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat umum ini, kita perlu merevitalisasi gerakan masyarakat sipil yang dalam beberapa tahun ini mengalami semacam dekadensi akibat efek polarisasi politik. Masyarakat sipil, dari berbagai latar belakang identitas suku, agama, ras dan afiliasi politik perlu membangun jaringan yang solid untuk bersama-sama menghalau dominasi korporasi busuk pelanggar HAM yang ironisnya disokong oleh negara.
Kita perlu melupakan sejenak semua sekat pembeda sosiologis, politis maupun ideologis untuk kemudian membangun kesadaran kolektif dalam melawan segala bentuk pelanggaran HAM. Musuh kita bukanlah individu atau kelompok yang berbeda agama atau pilihan politik. Musuh kita adalah kekuatan kapital yang berusaha mengendalikan negara demi kepentingan ekonomi-politiknya.
Revitalisasi jaringan masyarakat sipil akan menaikkan posisi tawar publik dalam diskursus wacana ekonomi dan sumber daya alam. Dengan jaringan yang solid, gerakan masyarakat sipil akan memungkinkan untuk melakukan intervensi terhadap negara agar mengubah haluan pembangunan agar lebih berorientasi pada kemanusiaan dan adaptif pada isu HAM.
Selain itu, revitalisasi gerakan masyarakat sipil juga akan membuka kemungkinan bagi praktik advokasi publik terhadap para penyintas pelanggaran HAM. Selama ini, para penyintas pelanggaran HAM cenderung tidak melakukan perlawanan lantaran ketiadaan dukungan nyata dari masyarakat. Advokasi publik ini dapat dilakukan dengan pengumpulan data korban pelanggaran HAM dan memastikan semua kasus pelanggaran HAM diselesaikan melalui jalur hukum.
Kita patut berharap momentum peringatan Hari HAM Internasional ini tidak hanya sekadar selebrasi belaka. Namun, lebih dari itu diharapkan mampu membangun kesadaran bersama terutama di kalangan pemerintah dan pemilik modal bahwa pembangunan nasional idealnya tidak hanya berorientasi pada capaian angka-angka statistik, namun juga menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Seperti diamanatkan konstitusi, pembangunan nasional haruslah mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks inilah penegakan HAM menjadi satu hal yang tidak bisa ditawar.
Siti Nurul Hidayah peneliti pada Center for the Study of Society and Transformation, alumnus Departemen Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(mmu/mmu)