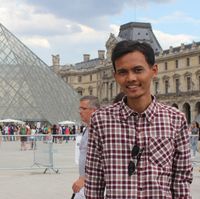Jaksa Agung menuai kecaman usai mengatakan bahwa kasus tindak pidana korupsi di bawah Rp 50 juta bisa diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara dan pembinaan bagi pelaku. Hal itu sebenarnya senada dengan pernyataan Wakil ketua KPK Alexander Marwata, Desember tahun lalu bahwa kepala desa yang korupsi cukup mengembalikan uang tanpa harus dipenjara lewat putusan pengadilan. Persoalannya menurut saya, korupsi, sebagaimana kejahatan atau penyimpangan lain, terjadi bergantung bagaimana ia didefinisikan.
Kita masih ingat, belum lama ini juga, seorang kakek dikeroyok sejumlah orang karena dituduh maling mobil hingga tewas. Padahal mobil yang dikendarainya adalah miliknya sendiri. Dari sini, tampaknya nasihat "jangan takut kalau Anda benar" perlu ditinjau ulang. Kakek itu nyatanya bukan maling, tapi takut dan kabur karena disebut maling. Poin krusialnya adalah seseorang yang tidak bersalah pun bisa disebut sebagai penyimpang ketika masyarakat mendefinisikannya sebagai penyimpang.
Secara sosial, penyimpangan tidak terjadi karena pilihan personal seseorang ataupun kegagalan seseorang memenuhi norma yang berlaku. Penyimpangan sosial bisa terjadi bergantung bagaimana masyarakat mendefinisikannya. Seseorang belum tentu bersalah, tetapi ketika ia didefinisikan oleh masyarakat sebagai penyimpang, maka ia menyimpang. Sebagaimana suatu aktivitas akan jadi menyimpang kalau didefinisikan demikian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di dalam ajaran-ajaran agama misalnya, kita bisa dengan mudah menemukan perbedaan satu aktivitas dianggap menyimpang atau tidak dalam kepercayaan yang berbeda. Sebagai contoh, muslim akan dianggap menyimpang ketika ia makan daging anjing dan makanan sejenis yang didefinisikan haram oleh ajaran Islam. Sementara dalam kepercayaan agama atau budaya lain seperti di sebagian Kota Tomohon, Sulawesi Utara daging anjing diperjualbelikan untuk dikonsumsi manusia.
Tidak hanya itu, secara hukum, kita juga bisa bandingkan aturan yang berbeda di berbagai negara. Di New Jersey, Amerika Serikat orang dilarang mengetik saat berjalan, atau larangan bagi perempuan mengenakan celana jeans ketat di Malaysia. Dua hal tersebut tidak dikategorikan sebagai penyimpangan di Indonesia, minimal menurut hukum yang berlaku. Sebaliknya, ada aturan-aturan yang dilarang di Indonesia tetapi legal di negara lain, seperti konsumsi ganja di Thailand dan Belanda.
Selain bergantung bagaimana ia didefinisikan, penyimpangan juga sangat bergantung pada siapa yang mendefinisikannya. Dalam hal ini, pihak yang memiliki kekuatan-kekuatan sosial cenderung kuat bisa menentukan definisi penyimpangan—sekaligus konformitas. Orang yang punya kuasa lebih, dia bisa menentukan mana tindakan yang dianggap menyimpang, mana yang tidak. Juga, mereka memiliki kuasa untuk menentukan pada derajat mana suatu aktivitas itu dikategorikan sebagai menyimpang.
Berbagai perubahan aturan yang ada di Indonesia menjadi contoh yang tepat untuk hal ini, seperti rencana alih definisi tanaman kelapa sawit. Sejauh ini, kelapa sawit masih dikategorikan bukan sebagai tanaman hutan baik oleh Food and Agricultural Organization (FAO) maupun Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI. Jadi, sederhananya, alih fungsi hutan dengan kelapa sawit merupakan deforestasi. Jika disepakati bahwa deforestasi merupakan bentuk pelanggaran, maka alih fungsi itu adalah penyimpangan. Tetapi, ketika sawit didefinisikan sebagai tanaman hutan, alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit itu tidak lagi menjadi penyimpangan.
Berbagai fenomena soal alih status lahan juga terjadi di banyak daerah. Untuk kepentingan tertentu, lahan-lahan hijau yang tidak boleh didirikan suatu bangunan diubah status lahannya agar bisa disulap jadi perumahan, pabrik, dan lainnya. Kita bisa telusuri kasus panjang pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah yang mendapatkan izin baru usai kalah di MA. Tentu saja, orang-orang yang punya modal, baik sosial maupun kapital, yang cenderung bisa mengubah itu.
Hal serupa bisa kita lihat dalam perubahan Statuta UI yang sebelumnya melarang rektor merangkap sebagai direksi pada BUMN/BUMD dan swasta. Setelah diubah, rektor menjadi boleh merangkap jabatan. Selain itu, ada juga perubahan peraturan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN) sehingga menambah jumlah anggota pansus dan aturan soal durasi karantina mandiri bagi pejabat setingkat Eselon I ke atas yang diubah menjadi bisa kurang dari 10 hari setelah heboh Mulan Jameela yang merupakan anggota DPR melanggar aturan karantina.
Sekali lagi, yang mendefinisikan itu semua adalah mereka yang punya kekuatan sosial. Baik aturan formal maupun non-formal, bisa diubah untuk memuluskan kepentingan pihak-pihak yang berkuasa. Perubahan aturan-aturan itu sebenarnya juga adalah proses pendefinisian perilaku menyimpang sekaligus pendefinisian pada derajat mana suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai penyimpangan.
Jika kembali ke kasus korupsi di Indonesia, kita jadi bertanya bagaimana korupsi didefinisikan oleh kekuatan sosial? Kenyataannya kita bisa melihat ada banyak kasus yang sanksinya cukup ringan. Juga, pernyataan Jaksa Agung di atas, seolah menegaskan bahwa korupsi boleh saja dilakukan, asal tidak banyak. Oleh karena itu, jika korupsi mau didefinisikan sebagai kejahatan luar biasa, maka berbagai kasus korupsi perlu direspons dengan cara-cara yang luar biasa pula, baik sanksi maupun aturannya. Seberapa pun itu korupsinya.
Logika sederhananya seperti anak kecil yang mengompol, tidak dikatakan menyimpang oleh orangtuanya. "Wajar, namanya juga anak kecil," kira-kira begitu respons orangtua. Seandainya sampai dewasa perbuatan itu dianggap wajar, baik oleh orangtua maupun oleh lingkungan sosialnya, maka anak itu akan terus mengompol karena itu bukanlah aktivitas yang didefinisikan sebagai penyimpangan. Sebaliknya, proses tidak mengompolnya anak merupakan respons atas keluhan orang ua dan lingkungan yang menganggap bahwa mengompol merupakan hal yang tidak wajar; menyimpang.
Sekali lagi, pada derajat mana kita menganggap korupsi ini sebagai kejahatan? Apakah didefinisikan sebagai kejahatan luar biasa atau para koruptor ini akan terus dibiarkan "ngompol" dan dianggap "wajar, namanya juga pejabat publik"?
Mukh. Imron Ali Mahmudi alumni Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia
(mmu/mmu)