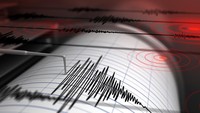Seharian ini, saya mengintip banyak kawan memajang aneka prestasi mereka selama setahun terakhir. Ada yang sudah tuntas membaca belasan buku, ada yang membuat review sekilas atas film-film Netflix atau drakor berseri-seri yang dikhatamkan secara maraton, ada yang berhasil menulis sekian puluh artikel, menerbitkan dua atau lima atau tujuh buku, dan sebagainya.
Kalau tanggal 25 selalu jadi ajang rutin perdebatan halal-haramnya ucapan selamat Natal, mendekati 31 Desember orang-orang sibuk menunjukkan kepada dunia, "Ini lho, di tahun ini aku sudah melakukan banyak sekali hal berguna!"
Saya termasuk tipe manusia yang belum pernah menderetkan buku-buku bacaan yang saya tuntaskan atau film-film yang saya tonton. Jujur, karena memang rasa-rasanya tidak cukup banyak buku yang saya baca sampai selesai dan bisa saya pamerkan. Tapi lebih dari itu, kadang muncul pertanyaan kecil, apa bedanya mengkhatamkan buku di tanggal 27 Desember dengan di 2 Januari? Sepertinya tak ada yang beda. Deretan huruf-huruf dan narasi dalam buku tak ada yang berubah. Pengalaman membaca, atau katakanlah pengetahuan yang nyantol di kepala kita juga bakalan persis sama, baik itu dibaca di hari terakhir 2020 ataupun di hari pertama 2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atau jangan-jangan, ada jenis orang yang mengejar dengan penuh ketegangan beberapa halaman buku pada menit-menit terakhir menjelang tutup tahun, lalu ketika tiba-tiba kembang api dilontarkan ke udara saat ia masih menyisakan dua lembar terakhir yang belum terkejar, orang itu seketika akan lunglai dan merasa gagal dengan target mereka di tahun 2020? Lalu kenapa dia selemas itu? Semata karena dia menetapkan satu batas imajiner yang tidak ada, namun dia meyakininya sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada, lalu dia tersiksa sendiri ketika merasa telah menabraknya.
Waktu memang ada. Mulai Tuhan, Einstein, sampai pesakitan di dalam penjara bicara tentang waktu. Setidaknya, ada bumi tempat kita berdiri yang terus berotasi, dan dari tempat kita berdiri itu kita melihat matahari merayap pelan sekali, ada malam yang semakin gelap, ada terang yang mengintip dan lambat laun menghadirkan kembali matahari, matahari yang merayap lagi, dan seterusnya. Tapi gabungan dari paket satu putaran matahari itu kita kalikan 365 dan tiba-tiba kita menciptakan angka-angka tahun.
Angka-angka itu akhirnya hadir dalam wujud seramnya, sebagai tonggak-tonggak yang kita tancapkan dalam fantasi di kepala kita sendiri, membuat kita menengok ke belakang dan bergumam, "Wah, sudah setahun ya. Cepet banget." Dan ucapan itu akan terdengar lebih menenangkan hati daripada kalimat lain yang menyakitkan, "Aduh, 20 tahun sudah. Selama ini ngapain aja?"
Kita menciptakan pancang-pancang sendiri, dan karenanya kita justru menciptakan tekanan-tekanan dalam hidup kita sendiri, termasuk menggoreskan luka-luka di hati kita sendiri.
Maka, kita mendengar tekanan itu muncul pula dalam angka-angka lain yang berjalan seiring dengan angka tahun, yaitu umur. "Tahun depan kamu sudah 30 tahun, teman-temanmu sudah menikah semua. Kamu gimana?" Ketika yang ditanyai itu akhirnya menikah pada usia 30, seolah-olah dia mengalami kegagalan besar untuk berpasangan secara resmi sesuai kesepakatan sosial pada usia kepala dua. Kita yang menontonnya pun seakan begitu yakin bahwa selisih satu tahun itu membuat perbedaan yang amat tajam dalam hal batas antara tua dan muda, kesiapan mental dalam membangun keluarga, kesegaran energi untuk berumah tangga, dan lain-lainnya.
Sialnya, perbedaan angka itu juga diperkuat oleh regulasi-regulasi, yang memang membuat aturan berdasarkan keumuman. Remaja berumur 17 tahun sudah boleh bikin SIM dan punya hak pilih untuk ikut Pemilu, misalnya. Itu berdasar pertimbangan kedewasaan diri, dan remaja yang beranjak dewasa sudah dianggap mulai matang dalam membuat pertimbangan-pertimbangan, entah itu pertimbangan saat mau membanting setir kendaraan, atau saat mau mencoblos capres pilihan. Dan, batasnya jelas, yaitu 17 tahun. Dengan regulasi eksak itu, seorang anak berumur 16 tahun lebih 10 bulan bakalan diposisikan kalah jauh kedewasaannya dengan anak lain yang persis berumur 17. Begitu, bukan?
Jadi, dengan angka-angka tahun, juga dengan angka umur yang didasarkan pada angka tahun, kita selama ini tak henti meng-eksak-kan sesuatu yang sesungguhnya tidak eksak. Kita memilah dengan tegas ruang-ruang imajiner yang kabur. Kita menciptakan garis batas yang kaku untuk wilayah yang sebenarnya sangat samar-samar. Lantas kita terpaku pada pemilahan tegas dan garis batas yang kaku itu, tunduk di hadapannya, kemudian menampari pipi kita sendiri manakala kita gagal dalam menyempurnakan ketaatan kita kepadanya.
Saya jadi ingat seorang kawan yang lupa umurnya. Ketika saya tanya seberapa tua dirinya, ia menjawab, "Sejak umur 30, waktu untukku sudah berhenti. Aku tak pernah mengingat-ingatnya lagi, ulang tahun juga tak pernah kurayakan lagi." Wah wah wah, betapa indah hidupnya. Betapa dia punya kemampuan tinggi untuk merayakan ruang lapang yang selama ini dipetak-petak oleh peradaban dan kebudayaan.
Saya ingin seperti dia. Agar tak peduli umur yang kian menua, agar tidak tersiksa perasaan "sekian puluh tahun berjalan tapi belum juga berbuat apa-apa", agar ruang dan waktu tergelar selapang-lapangnya. (Sampai kemudian suatu pagi anak perempuan saya yang obsesif dengan ulang tahun itu memeluk saya dan mengucapkan happy birthday, lalu buyarlah semuanya haha.)
Akhir kata, selamat Tahun Baru bagi yang masih merayakan. Tapi ingatlah bahwa hari pertama di tahun (yang seolah) baru itu sama persis dengan hari-hari sebelumnya. Di hari itu Anda tetap bisa menyusulkan beberapa halaman buku yang belum sempat tertuntaskan, melanjutkan satu episode dari drakor yang belum terkhatamkan, dan tentu saja sama sekali tidak masalah jika Anda menyambung pelaksanaan resolusi-resolusian di awal tahun lalu, yang ternyata lebih dari separuhnya belum terselesaikan.
Iqbal Aji Daryono penulis, tinggal di Bantul
(mmu/mmu)