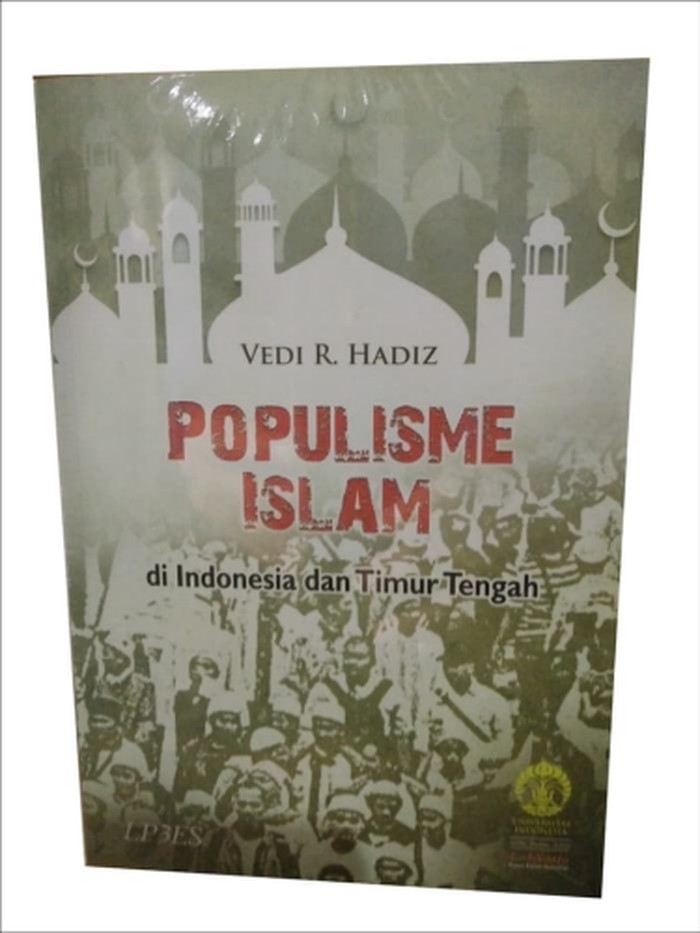Judul Buku: Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah; Penulis: Vedi R. Hadiz; Penerbit: Universitas Indonesia & LP3ES, 2019; Tebal: 431 Halaman
Tesis Francis Fukuyama mengenai "akhir sejarah" (the end of history) sebagai legitimasi terhadap demokrasi liberal dan kapitalisme berujung pada kebuntuan. Pengungsian besar-besaran masyarakat marginal dari Timur Tengah dan Afrika ke Barat, serta menguatnya sentimen anti-imigran di Eropa merupakan fenomena dari bangkitnya populisme. Kebuntuan tersebut tidak terlepas dari kontradiksi internal dalam pembangunan sosial kapitalisme yang memicu kemarahan massa terhadap sejumlah elite.
Kegagalan demokrasi liberal dalam menghadirkan kesetaraan politik berujung pada illiberal demokrasi. Begitu juga dengan ekonomi neoliberal yang menjanjikan kesejahteraan dan pertumbuhan, malah menghasilkan ketimpangan dan kesenjangan yang semakin parah. Dalam kondisi semacam itu, populisme hadir sebagai alternatif atas kebuntuan kapitalisme maupun sosialisme.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dewasa ini masyarakat global tidak hanya menyaksikan munculnya gerakan-gerakan populis, tapi juga kemenangan rezim populis. Di benua Amerika, kemenangan rezim populis --baik yang berhaluan "kiri", "kiri-tengah", dan "kanan"-- telah berlangsung sejak akhir 90-an yang diawali oleh kemenangan Hugo Chavez di Venezuela hingga yang terakhir kemenangan Donald Trump di Amerika dan Jair Bolsonaro di Brasil.
Kemenangan rezim populis tidak serta merta berada pada posisi menolak demokrasi liberal dan neoliberalisme. Karena esensinya, populisme dengan demokrasi maupun neoliberalisme dalam konteks tertentu saling mendukung. Maka perkembangan dunia ke depan dihadapkan pada tantangan, apakah populisme berpotensi membuat warga dunia meninggalkan tatanan demokrasi liberal dan ekonomi neoliberal, atau justru sebaliknya.
Untuk Indonesia, populisme sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak era kolonial Hindia-Belanda sudah muncul gerakan populis dalam menentang elite kolonial demi pembangunan bangsa. Hingga pasca Kemerdekaan, masa Orde Lama, populisme berlangsung dalam sebuah diskursus anti elite-kolonial menjadi anti elite-imperial. Pada awal-awal kekuasaan Orde Baru-Soeharto muncul sebuah wacana membangun sosialisme Indonesia dan melanjutkan cita-cita revolusi yang belum selesai. Meski pada akhirnya proses depolitisasi dan deideologisasi dalam rangka memutus hubungan antara elite politik dengan massa rakyat (partai) sempat meredupkan populisme hingga akhir kekuasaan Orde Baru.
Populisme kembali mendapat momentumnya ketika Indonesia diterpa krisis moneter 1997. Aspirasi kerakyatan mengemuka dalam bentuk perlawanan terhadap rezim penindas dan korup. Dalam buku Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah ini Vedi R. Hadiz menjelaskan populisme yang sedang berkembang di Indonesia berbeda dengan populisme pada umumnya. Inti dari buku ini adalah Indonesia, Mesir, dan Turki. Ketiga negara tersebut ada kesamaan, di samping mayoritas penduduk Muslim, pengalaman kolonialisme, dan kemerdekaan nasional. Dengan pendekatan ekonomi-politik dan sosiologi-historis, Hadiz berpendapat bahwa trajektori populisme di Indonesia cenderung mengarah pada kegagalan. Penekanan analisis terhadap faktor-faktor material menjadi penyebab atas kegagalan dari populisme di Indonesia.
Dalam buku tersebut, Hadiz menjelaskan bahwa populisme yang sedang berkembang di Indonesia adalah populisme Islam --varian dari populisme. Menurutnya, populisme Islam merupakan aliansi multikelas yang asimetris yang mengidentifikasi dirinya sebagai umat (the ummah) vis-a-vis elite sebagai respons atas kontradiksi sosial dalam pembangunan kapitalisme kontemporer. Populisme Islam juga melakukan mobilisasi dan homogenisasi beragam ketidakpuasan "massa" yang sangat berbeda-beda melawan "elite" tertentu.
Namun homogenisasi dalam populisme Islam tidak terjadi lewat the people, melainkan the ummah (umat). Dalam populisme islam konsep "umat" digunakan menggantikan konsep the people. Meski umat kerapkali dipahami dalam kerangka supranasional, namun seiring munculnya gerakan Islam melalui perjuangan nyata mendorong perkembangan pemahaman yang lebih bersifat nasional. Pemahaman semacam itu di perlukan agar dapat menjembatani kepentingan sosial yang beragam dan saling bertentangan.
Sebagai aliansi multikelas yang asimetris dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat, pada dasarnya sangat problematis. Sebab istilah "kelas" sendiri dipahami bukan sekadar agregat individu sebagai satu kelompok sosial yang punya sejarah dan tempat dalam komunitas Islam, melainkan agregat individu yang disamakan berdasarkan perbedaan pendapatan, level pendidikan, dan kepemilikan terhadap alat produksi. Tanpa mengacu pada perbedaan tersebut, antara miskin dan kaya, maka aliansi multi kelas atas nama umat mengandung kontradiksi internal. Beragam kepentingan yang berbeda-beda akan berbenturan --hingga pada taraf tertentu saling menegasi.
Dalam analisisnya tentang trajektori populisme Islam. Hadiz menjelaskan bahwa kemunculan populisme Islam tidak terlepas dari warisan dari konflik sosial di era Perang Dingin yang mendera gerakan politik dan sosial Islam. Faktor material dipandang turut berpengaruh atas terbentuknya relasi sosial dan strategi Islam politik. Hasilnya outcame dari populisme Islam di tiga negara tersebut berbeda. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin (IM) berhasil menguasai ranah Civil Society dalam waktu lama. Ketika Presiden Mesir Hosni Mubarak tumbang, IM menjadi kekuatan politik yang terkonsolidasi dengan menguasai negara untuk sementara waktu.
Begitu juga dengan kasus Turki, evolusi populisme Islam berujung pada kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Sedangkan di Indonesia, dalam sejarahnya populisme Islam gagal menguasai negara maupun civil society, baik ketika menggunakan strategi non-elektoral dalam kasus Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DII/TII), maupun elektoral kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Organisasi masa Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia tampaknya tidak cukup mampu menjadikan dirinya seperti IM di Mesir. Fragmentasi umat muslim di Indonesia baik dari level isu dan organisasional merupakan sala satu faktor kegagalan mereka dalam menguasai arena civil society. Tekanan terhadap islam, di samping menekan kekuatan progresif lainnya, selama Orde Baru membuat kekuatan islam berada di pinggiran. Pendirian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai wahana elektoral Islam, tidak lantas mempermulus agenda umat. Ada banyak faktor yang di perlihatkan Vedi Hadiz dalam buku ini seperti perebutan sumber daya material elite oligarki selama masa Orde Baru.
Pasca Reformasi, wahana elektoral mulai bermunculan dan umat memiliki beragam pilihan. Setidaknya terdapat tiga partai islam yang mampu bertahan, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Seperti dijelaskan Hadiz, bahwa populisme Islam dalam bentuknya yang baru memiliki basis-basis sosial yang lebih luas dan beragam sekaligus dapat berjuang bebas melalui jalur elektoral. Karena penekanan pada basis material sebagai faktor penentu keberhasilan dari politik Islam di Indonesia. Maka kegagalan politik Islam melalui jalur elektoral turut disebabkan oleh ketiadaan borjuis muslim yang dominan.
Sebagai bahan refleksi untuk memahami dinamika politik Islam yang terjadi di masa lampu dan sekarang. Buku ini memberikan cara baru dalam memahami perkembangan politik Islam yang telah mengalami transformasi di abad modern. Karenanya, penting untuk di baca oleh para aktivis, akademisi, politisi dan pemangku kebijakan.
Rudi Hartono anggota di Forum Intelektual Nuhu Evav Malang
(mmu/mmu)