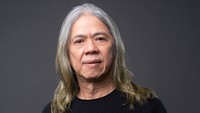Komentar Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini soal kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu mengerem suplai uang (money supply) sempat ramai diperbincangkan. Banyak yang menyambutnya sebagai kritik jujur dari seorang pejabat senior, yang jarang muncul di ruang publik. Namun kita jangan berhenti di sana. Karena yang penting bukan sekadar kenapa sampai seperti ini, tetapi kenapa kebijakan itu bisa terbentuk demikian?
Banyak pula yang bertanya, jika memang sesederhana itu menaruh dana pemerintah di perbankan agar likuiditas pro pertumbuhan, kenapa dulu Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak melakukannya? Apakah beliau tidak tahu?
Ketika Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik BI dan Kemenkeu karena terlalu mengerem suplai uang, ia sejatinya sedang menunjukkan keterbatasan struktural arsitektur hukum kita. BI terikat pada target inflasi, Kemenkeu terikat pada defisit dan tata kelola kas. Maka, meskipun sama-sama paham risiko kontraksi likuiditas, tangan mereka terikat oleh KPI dan mandat undang-undang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para teknokrat kita, baik di Kemenkeu maupun di Bank Indonesia, paham betul apa yang terjadi. Tetapi ada ortodoksi kebijakan dan kerangka hukum yang membatasi ruang gerak mereka. Kenapa sebelumnya penempatan dana di bank umum tidak dilakukan dan UU perbendahaan mempersulitnya?
Sekali lagi, jawabannya adalah di ortodoksi. Filosofi dari pemisahan kebijakan moneter dan fiskal membuat penempatan dana pemerintah di Bank Umum mendatangkan pertanyaan. Kalau memang ini untuk likuiditas, ini seharusnya domain fiskal apa moneter? Ini perdebatan yang jamak muncul. Di kondisi normal dimana transmisi moneter lancar, ini tak perlu terjadi, tapi didalam kondisi extraordinary, fiskal harus ikut membantu untuk menyelamatkan perekonomian.
UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara mengunci tata kelola fiskal dengan disiplin defisit. UU Bank Indonesia mensyaratkan kestabilan rupiah, untuk BI juga ada Inflation Targeting Framework yang digunakan sejak tahun 2005 (yang lalu berubah jadi flexible ITF), lalu ada UU LPS dan UU OJK memisahkan lagi fungsi stabilitas keuangan.
Semua UU itu lahir di awal 2000-an, pasca krisis Asia, ketika trauma inflasi dan disiplin IMF menjadi roh utama. Wajar pada masanya, tetapi dunia sudah berubah. Jaman dulu kita menghadapi Euforia Globalisasi, pertumbuhan ekonomi momentumnya selalu besar dari perdagangan internasional, inflasi tinggi karena sisi permintaan yang tinggi pula, sehingga pemerintah dan bank sentral cukup menjadi jangkar stabilitas, namun semua itu berubah semenjak terjadi trade war dan berbagai disrupsi teknologi.
Zaman Baru, Shock Baru
Hari ini kita hidup di era di mana supply shock datang bertubi-tubi: pandemi, perang Ukraina, geopolitik energi, perubahan iklim, fragmentasi rantai pasok, dan technological progress. Kerangka Inflation Targeting Framework dibangun dalam asumsi bahwa supply shock jarang terjadi, dan manajemen ekonomi dibangun untuk mengendalikan demand-driven inflation.
Secara teori makro (contohnya model New Keynesian), kita punya trade-off jangka pendek antara inflasi dan output: ketika terjadi kenaikan harga input, energi, pangan, atau gangguan rantai pasok, harga terdorong naik, sementara output justru tertekan karena biaya produksi meningkat, margin menyusut, konsumsi dan investasi melemah.
Supply shock mengubah sifat hubungan ini: inflasi melonjak bukan karena permintaan berlebih, melainkan karena sisi penawaran terganggu. Kalau kerangka kebijakan lama tetap dipakai, dengan bank sentral terpaku pada target inflasi dan pemerintah menahan defisit, maka satu-satunya cara "menjinakkan" inflasi adalah dengan menekan output lebih jauh ke bawah.
Suku bunga dinaikkan keras, permintaan ditarik turun, sementara fiskal tidak memberi bantalan. Hasil akhirnya, ekonomi bisa terjebak dalam negative output gap yang panjang: pertumbuhan hilang momentum.
Lebih jauh lagi, perubahan teknologi ikut memperlemah efektivitas trade-off tradisional kebijakan sektor keuangan. Otomatisasi, digitalisasi, dan model bisnis berbasis platform membuat Phillips Curve semakin datar: pasar tenaga kerja kini lebih tidak responsif terhadap fluktuasi output, disamping kebutuhan tenaga kerja dalam banyak sektor memang lebih rendah dibanding dekade lalu, sehingga bahkan jika output turun, upah dan inflasi tenaga kerja tidak serta-merta terkendali.
Artinya, kebijakan moneter dampaknya ke peningkatan pendapat tenaga kerja tidak sekuat di masa lalu. Semua orang bertanya-tanya tentang transmisi moneter via kredit yang tak kunjung datang. Bank Sentral-pun jadi semakin mengandalkan kebijakan macroprudential dibandingkan kebijakan moneternya.
Di sisi lain, Ini justru memperpanjang luka di sisi pertumbuhan tanpa hasil yang sebanding di sisi harga. Kita harus berubah, kalau tidak, akan terjadi ironi yang luar biasa, dimana otoritas-otoritas berhasil melaksanakan mandatnya dengan baik, tapi dengan berujung pada output ekonomi yang jauh dari maksimal.
"ibaratnya, harga cabai naik karena gagal panen, lalu kita menanggapi dengan menjaga bunga kredit tinggi, tanpa memberikan tambahan investasi petani cabe untuk menurutnkan harga, hasilnya, pedagang tetap mahal, tapi pembeli makin sepi", ekonomi pun nelangsa.
Terkait dengan ini, Literatur terbaru menunjukkan bahwa supply shock tidak sekadar kejutan sementara, tetapi bisa meninggalkan "scars" jangka panjang: kapasitas produksi melemah, investasi tertahan, dan produktivitas terganggu. Fornaro (2023) menyebut bahwa bila kebijakan moneter merespon terlalu agresif, luka itu justru semakin dalam, output gap negatif bisa bertahan lebih lama, dan ekonomi kehilangan momentumnya.
IMF Working Paper (2025) yang berjudul Inflation Targeting and the Legacy of High Inflation menambahkan dimensi lain: ketika ekspektasi inflasi masyarakat sudah terbentuk dari episode inflasi tinggi sebelumnya, bank sentral terdorong untuk mendinginkan ekonomi ekstra keras agar kredibilitas terjaga. Akibatnya, output gap negatif dipertahankan lebih lama dari yang ideal, demi memastikan inflasi kembali ke jalur target.
Hal serupa dimodelkan oleh Billi (2020, IJCB), yang menunjukkan bahwa kerangka moneter agresif saat cost-push shock justru memperlebar dan memperlama negative output gap. Ignacio Escanuela Romana (2020, Keynesian models of depression) bahkan menyebut supply shock tanpa stimulus permintaan bisa bertransisi menjadi "depresi", penurunan aktivitas yang berkepanjangan. Tingkat suku bunga BI yang masih tinggi, ditengah inflasi yang sempat menyentuh 1%-an tentunya menjadi hal yang patut kita soroti.
Konteks Indonesia: Menjaga Rupiah, Menekan Output
Untuk negara berkembang seperti Indonesia, problem ini menjadi lebih kompleks. Bank Indonesia tidak hanya menjaga inflasi, tetapi juga kurs rupiah. Dalam situasi supply shock global (energi, pangan, geopolitik), tekanan ke rupiah bisa datang deras dari arus modal keluar. Agar kurs stabil, BI sering menaikkan suku bunga lebih tinggi daripada yang semestinya dibutuhkan oleh dinamika domestic, atau juga lewat SRBI yang pada dasarnya juga bersifat kontraktif.
Ditambah lagi dengan adanya perubahan teknologi yang membuat kebutuhan tenaga kerja semakin sedikit, kebijakan yang relatif kearah kontraksi akan membuat dampak kepada lapangan pekerjaan semakin berat. Semakin sedikit perusahaan yang kuat menanggung situasi ini.
Artinya, Indonesia menghadapi double squeeze: Supply shock sudah menekan output dari sisi produksi, Moneter ketat demi stabilisasi kurs menekan permintaan lebih jauh. Jika fiskal juga tetap dibatasi defisit rendah, maka tidak ada bantalan yang cukup untuk menjaga pertumbuhan. Inilah mengapa luka supply shock di Indonesia berpotensi lebih dalam dibanding negara maju karena beban menjaga stabilitas kurs membuat kebijakan moneter kita semakin bias kontraktif, dan disiplin fiskal kita juga berujung pada situasi yang kontraktif pula.
Sebagai contoh, Bank Indonesia memang berhasil mengendalikan volatilitas rupiah dalam beberapa tahun terkahir lewat SRBI, tapi ini berujung pada money supply yang lebih rendah dari seharusnya, dan disiplin fiscal kita berhasil terkait defisit APBN dibawah 3% PDB, tapi momentum ekonomi lebih rendah, runtuhnya permintaan kelas menengah serta lambatnya penyerapan anggaran menjadi hal yang sangat ironis.
Sangat banyak curahan hati yang penulis dengar semasa kebijakan ini diambil, tapi akhirnya, tujuan kebijakan tercapai memang, kestabilan bisa kita dapatkan.
Ditengah minimnya pertumbuhan, investor pasar keuangan pun juga akan bertanya-tanya akan prospek Indonesia, jika kondisi ini terjadi lebih jauh.
Pada ujungnya, tidak ada yang salah disini, karena institusi-institusi keuangan kita menjalankan peran sesuai mandatnya. Dalam hal ini, penulis menyarankan untuk mengkaji ulang kembali landasan hukum, atau UU terkait dengan sektor keuangan di Indonesia, untuk perluasan mandat, yang tidak hanya kestabilan, melainkan lebih kearah support pertumbuhan.
Beberapa pembahasan yang mungkin perlu dipertimbangkan antara lain:
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (dan revisinya, terakhir UU P2SK 2023). Pasca krisis, UU ini menegaskan independensi BI dengan satu tujuan: stabilitas rupiah (dimaknai sebagai inflasi + nilai tukar).
Dalam kondisi saat ini, mandat sebaiknya diperluas, tetap independen, tapi dengan dual mandate: stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan/pekerjaan berkelanjutan. Koordinasi fiskal-moneter juga harus dilembagakan, karena kemungkinan besar, shock yang terjadi dalam fase perubahan teknologi yang cepat dan geopolitik masih akan sering terjadi.
Lalu, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga harus dibahas. UU ini dulu Melahirkan disiplin defisit & utang, selaras dengan semangat jamannya.
Namun, di kondisi saat ini, negara butuh fleksibilitas fiskal menghadapi supply shock, perang dagang, dan perubahan teknologi yang membawa dampak terhadap merosotnya pasar tenaga kerja. Dalam hal ini, harus ada ruang countercyclical fiscal policy yang jelas, misalnya deficit bisa melebih batas dalam waktu tertentu sampai perbaikan ekonomi tercapai.
Di sisi lain, di dalam fase ketidakpastian seperti saat ini, untuk kembali menyatukan ekonomi, juga dibutuhkan hubungan kelembagaan yang lebih dekat diantara otoritas moneter, fiskal dan juga pengawasan sektor keuangan dan penjamin deposit. Bisa jadi KSSK nanti dibutuhkan untuk bertemu lebih sering dalam kerangka macro coordination, bukan hanya crisis management dan crisis prevention.
Dunia Sudah Bergerak
Di era kini, supply shock lebih sering daripada demand shock. Harga pangan, energi, iklim, dan geopolitik dan perubahan teknologi dan pasar tenaga kerja yang konstan terjadi mengubah total sisi penawaran. Dalam kondisi seperti ini, kerangka Inflation Targeting Framework ataupun flexible inflation targeting framework menjadi tumpul. Saat ini, banyak negara sudah mulai melakukan perubahan:
The Fed (AS) mengadopsi Flexible Average Inflation Targeting (FAIT) yang memberikan keleluasaan yang lebih besar, Jepang bertahun-tahun menjalankan Yield Curve Control untuk mendukung pembiayaan jangka panjang. IMF bahkan kini mendorong Integrated Policy Framework (IPF), yang menggabungkan kebijakan moneter, fiskal, intervensi valas, dan makroprudensial untuk menghadapi shock yang kompleks. Di sisi lain, Bank of England juga mulai melakukan kebijakan yang lebih mengedepankan beberapa skenario, disbanding satu hal yang rigid.
Untuk negara berkembang, India juga sedang melaksanakan beberapa perubahan penting, dan lebih toleran terhadap inflasi yang bersumber dari supply shock. Bahkan kalangan kademianya pun berpendapat bahwa Diskursus akademis India sekarang menekankan bahwa rigid inflation targeting berisiko "overkill" di negara emerging yang rawan supply shock.
Terkait dengan ini beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh BI dan Kementrian Keuangan:
1. Respons moneter harus "tertarik ke permintaan" saat supply shock. Artinya: tidak otomatis menaikkan suku bunga setinggi mungkin ketika inflasi naik karena komponen biaya. Bank sentral harus menyeimbangkan antara menahan inflasi dan menjaga pertumbuhan. Real Interest Rate harus dibiarkan rendah dalam waktu lama.
2. Fiskal perlu peran counter-balancing. Jika defisit dan belanja publik sangat dibatasi, maka tidak ada kekuatan yang menopang permintaan ketika moneter mengetat. Itu membuat output gap negatif justru berkepanjangan.
3. Mandat kebijakan moneter harus lebih fleksibel. Karena tekanan supply shock sering bersifat sementara untuk beberapa komponen (energi, impor pangan), bank sentral perlu punya ruang untuk "melihat lewat" inflasi sementara, tanpa kehilangan kredibilitas.
4. Mandat jangka panjang dan koordinasi lembaga harus diperkuat. Tanpa koordinasi BI-fiskal-stabilitas keuangan + kebijakan struktural, kerangka yang ketat akan cepat memunculkan disfungsi. Agenda reformasi hokum dan bauran kebijakan juga jangan dilupakan.
Pada akhirnya, "Zaman baru menuntut alat baru. Jika hukum lama lahir dari trauma, maka hukum baru harus lahir dari keberanian. Bangsa ini layak mendapatkan lebih dari sekadar stabilitas, kita butuh pertumbuhan yang hidup, pekerjaan yang bermakna, dan rupiah yang benar-benar melayani rakyat."
Fakhrul Fulvian. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia.
Tulisan ini ditujukan untuk bankir, fund manager, ekonom dan pengambil kebijakan moneter, fiskal dan sektor keuangan.
(rdp/rdp)