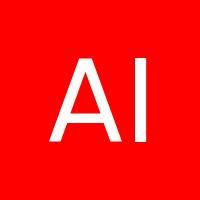Secara politik, swasembada beras adalah isu yang punya jual tinggi untuk menarik simpati pemilik suara, karena masifnya jumlah rumahtangga petani di Indonesia. Oleh karena itu jualan swasembada beras adalah jualan penting dalam proses politik khususnya dalam pemilihan raya Indonesia. Mengabaikan isu swasembada beras bisa dipersepsikan tidak berpihak kepada wong cilik yang salah satu komponen pentingnya adalah petani.
Pencapaian swasembada beras tahun 1984 diselebrasikan oleh Lembaga pangan dunia (FAO), di mana presiden Soeharto diundang untuk menyampaikan pidato di FAO tanggal 14 November 1985 pada acara ulang tahun FAO ke 40 sebagai bentuk penghargaan FAO terhadap pencapaian swasembada beras Indonesia. FAO memberikan medali emas kepada Soeharto, bertuliskan "From Rice Importer to Self Sufficiency". Medali bergambar timbul wajah Soeharto di satu sisi dan petani menanam padi di sisi lain (VOI, 2022). Secara nasional produksi padi meningkat dari 18 juta metrik ton di tahun 1969 menjadi 38,1 juta metrik ton di tahun 1984 naik 112%. pada periode yang sama produktivitas padi naik dari 2.5 ton per ha menjadi 4.1 ton atau naik 64% (USDA, 2012).
Namun, pencapaian tersebut tidak bisa direplikasi dengan mudah. Soeharto memiliki keunggulan historis yang tidak dimiliki presiden era reformasi karena alasan berikut: Pertama, era Soeharto berkuasa khususnya di era 1970-1980an geopolitik global masih diwarnai oleh perang dingin di mana dunia hanya terdiri atas dua kutub yakni Barat dan Timur (komunis). Kekuatan politik global Barat punya kepentingan besar agar Indonesia bebas dari pengaruh kekuatan komunis sehingga mereka mendukung mati-matian regim berkuasa yang anti komunis saat itu yang direpresentasikan pemerintahan Soeharto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dukungan at all cost perencanaan dan strategi Soeharto untuk mencapai swasembada baik dalam bantuan finansial atau teknologi, yang tujuan utamanya agar agar Indonesia tidak berorientasi kekuatan kiri dunia saat itu. 60 persen pembangunan lima tahun pertama Orde Baru di tahun 1969 bersumber dari bantuan luar negeri (Mas'oed, 1983). Di samping itu ada dukungan dari oil boom di tahun 1970an di mana Indonesia berposisi sebagai negara net exporter untuk migas saat itu yang memperkuat sisi finansial pencapaian swasembada beras. Saat ini Indonesia berposisi sebaliknya net importer migas sejak tahun 2003.
Pasca perang dingin, Indonesia tidak punya kemewahan seperti itu lagi. Paradigma perdagangan bebas yang lebih mendominasi hubungan ekonomi di tataran global. Institusi ekonomi global seperti Bank Dunia, WTO, IMF dan negara-negara pendukungnya lebih suka semua negara yang menghadapi kekurangan pasokan pangan untuk membeli pangan tersebut dari negara lain. Kebijakan subsidi dan proteksi terhadap pangan termasuk beras dalam rangka mencapai untuk swasembada tidak akan didukung secara finansial, teknologi dan politik dan aturan main perdagangan internasional. Kita tentu masih ingat ketika Bulog dihilangkan kekuatan monopoli dalam ekonomi pangan Indonesia via LoI dengan IMF pada saat krisis finansial Asia Fasifik 1997-1998, yang bersamaan dengan tumbangnya kekuatan monopoli politik presiden Soeharto saat itu.
Yang kedua, swasembada beras Indonesia tahun 1984 adalah proses panjang pembangunan pertanian dalam satu kekuasaan tanpa disrupsi politik, suatu kemewahan politik yang tidak akan bisa dimiliki seorang presiden Indonesia era reformasi. Pak Harto mencapai swasembada tersebut setelah kurang lebih hampir 4 periode kekuasaannya (20 tahun), kalau dihitung sejak jatuhnya orde lama (1966). Pak Harto butuh waktu hampir 20 tahun kekuasaannya untuk mencapai swasembada pangan, dengan dukungan penuh semua kekuatan politik, birokrasi, militer dan semua stakeholder bangsa.
Pasca Orde Baru, tidak ada figur politik yang memiliki kemewahan seperti yang dinikmati Soeharto—privilege khas rezim non-demokratis. Di era reformasi, demokrasi menghapus kemewahan itu dari jangkauan presiden manapun. Kini, presiden hanya diberi waktu maksimal 2 periode kekuasaan (10 tahun) untuk menjalankan agenda ketahanan pangan, dengan tekanan menunjukkan hasil dalam 5 tahun pertama mereka harus bisa meyakinkan publik bahwa ada progres yang telah mereka wujudkan terkait ketahanan pangan. Hampir dapat dipastikan dalam realitasnya seorang presiden dan parpol pendukungnya hanya peduli dengan target pencapaian 5 tahunan bukan yang berorientasi jangka panjang.
Hari ini demokrasi telah menghadirkan dialetika bahkan oposisi dan resistensi antara kekuatan politik di pemerintah pusat atau bahkan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah pasca orde baru telah menghadirkan daerah yang bisa punya solusi berbeda terkait pembangunan pertanian dan ketahanan pangannya dibanding dengan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat.
Ketiga, di era Soeharto, peningkatan produksi melalui cara perluasan lahan secara efektif masih bisa dilakukan via program transmigrasi. Di era reformasi bukan saja sulit untuk mencetak lahan pertanian baru, ditunjukkan dengan program food estate yang dilakukan pemerintah sepanjang era reformasi belum mampu menunjukkan hasil yang diharapkan karena kendala sulitnya mendapatkan lahan yang luas dan subur untuk program tersebut, tetapi juga konversi lahan pertanian ke penggunaan lain terjadi dengan masif.
Berdasarkan uraian di atas, saya menyarankan agar swasembada beras diganti dengan swasembada pangan lokal berbasis daerah. Masing-masing Kabupaten/Kota menentukan jenis pangan daerahnya yang ingin mereka tingkatkan produksinya untuk kepentingan masyarakatnya sehingga menjadi komoditas pangan lokal penting daerah tersebut, termasuk bantuan sosial pangan daerah itu juga menggunakan pangan lokal tersebut. Strategi pencapaian swasembada pangan berbasis kabupaten kota ini lah yang lebih padu dan selaras dengan kondisi sistem politik Indonesia, situasi geopolitik dan tantangan perubahan iklim global ke depan.
Andi Irawan. Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Bengkulu, Ketua Bidang kebijakan Publik ASASI (Perhimpunan Akademisi dan Saintis Indonesia)
Simak juga Video: Zulkifli Hasan Bicara Percepatan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air