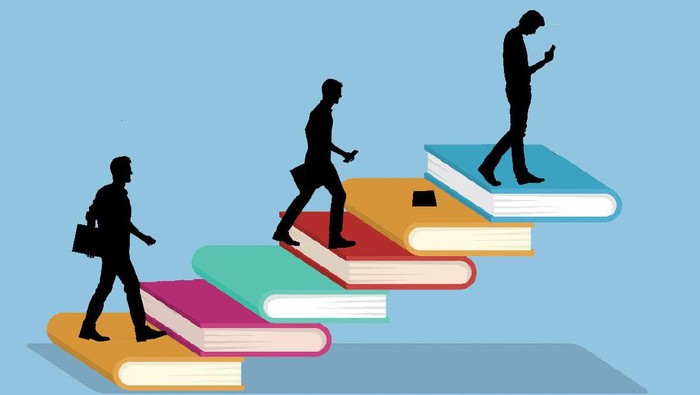"Mas, tolong cukup ditulis nama saya saja tanpa gelar," pinta salah seorang tokoh, sebut saja Pak Udin, ketika saya undang ke sebuah acara bedah buku. Awalnya, kami menaruh gelar Dr. (H.C.) atau Doctor Honoris Causa di depan namanya. Namun ia keberatan dan memilih menggunakan namanya saja tanpa embel-embel gelar. (Di tulisan ini saya sengaja tidak menulis nama aslinya demi penghormatan saya kepada Pak Udin yang sangat rendah hati).
Padahal Pak Udin mendapatkan gelar itu dari kampus ternama. Gagasan dan kiprahnya dalam kehidupan keberagaman yang harmonis di Indonesia membuat sebuah kampus menganugerahi Pak Udin yang juga mantan menteri dengan gelar kehormatan. Namun ia tampaknya tidak tertarik mengumbar-umbar gelar itu. Bahkan kabarnya, Pak Udin awalnya enggan menerima gelar doktor kehormatan karena merasa kurang pantas.
Selain Pak Udin saya juga mengapresiasi Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang membuat sebuah surat edaran. Ia meminta agar deretan gelar akademik ditanggalkan dari namanya apabila tidak menyangkut kebutuhan akademik. Ia beranggapan bahwa gelar akademik adalah bentuk tanggung jawab dan amanah, bukan status sosial. Baginya, gelar akademik semestinya menjadi tanda seseorang dinyatakan lulus menempuh pendidikan di kampus.
Tetapi muncul banyak kasus gelar akademik di berbagai tingkatan diperjualbelikan. Salah satu isu besar yang sedang ramai diperbincangkan adalah pemberian Gelar Doktor Kehormatan dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) kepada artis Raffi Ahmad. Gelar ini disematkan kepada Raffi Ahmad atas kontribusinya dalam pengembangan industri hiburan di Indonesia. Hal ini memantik perbincangan karena banyak orang yang baru mendengar nama kampus tersebut. Dalam posting-an di media sosialnya, Raffi Ahmad menyebut kampus UIPM berasal dari Thailand.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gelar untuk Raffi itu memang bukan berasal dari kampus ternama seperti Chulalongkorn, Mahidol, atau Chiang Mai yang bergengsi. Nama kampusnya konon tidak terindeks di database kampus global. Oleh karenanya, sebagian orang menaruh curiga yang kuat. Salah satu pengguna media sosial yang tinggal di Thailand kemudian menelusuri alamat kampus tersebut. Ternyata kampus yang diklaim memiliki cabang di beberapa negara termasuk Indonesia itu tidak dikenal oleh penduduk setempat. Alamat 'kampus' itu berupa ruko dan apartemen yang sama sekali tidak terlihat kampus.
Pertanyaan dan kegelisahan publik itu kemudian ditanggapi oleh pihak kampus. Melalui keterangan media, UIPM mengakui bahwa alamat di Thailand bukanlah kampus pada umumnya. Sebab kampus ini menerapkan sistem total daring yang tidak mengharuskan adanya bangunan fisik. Mereka juga menyebut bahwa kampusnya sudah terakreditasi melalui lembaga internasional, salah satunya dari Order of Kingdom Prussia. Penjelasan ini semakin membuat orang penasaran karena Kerajaan Prussia yang juga merupakan negara kelahiran pemikir besar Karl Marx sudah bubar lebih dari seabad yang lalu.
Sebelum sang artis, seorang politisi juga dipertanyakan bagaimana ia mendapatkan gelar sarjananya. Secara usia, ketika mendapat gelar tersebut, politisi itu usianya sudah 40-an tahun. Artinya, gelar tersebut didapatkan dengan cara 'tidak wajar'. Setelah ditelusuri, ternyarta kampus yang memberinya gelar sudah tutup karena tidak memiliki izin dari Dikti. Kampus tersebut bertempat di sebuah ruko yang diduga menjadi produsen gelar akademik selama bertahun-tahun.
Masyarakat Tontonan
Pemberian Gelar Kehormatan memiliki landasan hukum yang jelas di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) disebutkan bahwa: Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.
Peraturan ini menjelaskan pula mekanisme pemberian Gelar Kehormatan, di antaranya syarat perguruan tinggi tersebut pernah menghasilkan sarjana dengan gelar ilmiah Doktor dan memiliki Fakultas atau Jurusan yang membina dan mengembangkan bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan atau karya bagi pemberian Gelar (Pasal 3). Gelar Kehormatan mensyaratkan adanya juga persetujuan Menteri (Pasal 4 s/d 8).
Pertanyaannya, apakah semua aspek di atas, terutama persetujuan Menteri, sudah dipenuhi? Kementerian terkait perlu ambil bagian untuk memberi penjelasan ke publik agar tidak menjadi bola liar.
Saat ini kecenderungan masyarakat adalah menghakimi Raffi Ahmad sebagai penerima gelar tanpa mengulik aspek lain yang menentukan. Raffi Ahmad bisa jadi memang layak menerima sebuah Gelar Kehormatan dengan prasyarat-prasyarat tertentu. Sederhananya, Raffi Ahmad punya hak konstitusional mendapatkan gelar apapun seperti masyarakat pada umumnya. Namun, semua prasyarat harus terpenuhi untuk menjamin asas keadilan dan keterbukaan, termasuk status legalitas kampus yang saat ini menjadi perdebatan hangat di ruang maya.
Di luar geger Raffi Ahmad, kegelisahan gelar akademik menjadi komoditas mulai nyaring disuarakan, terutama dari kalangan akademisi 'tulen'. Selain kampus ruko, kampus-kampus 'besar' tak luput menjadi bagian dari marketisasi ruang-ruang akademik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian kampus terkenal membuka kelas-kelas khusus bagi pejabat, politisi, dan kategori orang sibuk lainnya, demi mendapatkan gelar penunjang jenjang karier.
Di sisi lain, pengelolaan kampus yang membutuhkan biaya jumbo membuat praktik marketisasi ruang akademik ini kian subur. Apalagi banyak kelas-kelas khusus merupakan bentuk kerja sama antara kampus dengan perusahaan besar. Transaksi gelar ini membuat kampus terlihat seperti marketplace.
Mengapa ada banyak orang begitu terobsesi dengan gelar tanpa melalui proses yang semestinya? Saya jadi teringat dengan tesis seniman Prancis bernama Guy Debord (1931-1994). Pada 1967, Debord pernah menggambarkan kehidupan yang mendewakan citra yang disebutnya sebagai masyarakat tontonan (the society of spectacle). Dalam masyarakat tontonan, penampakan (appereances) lebih penting daripada kepemilikan (having). Yang penting apa yang terlihat dibandingkan apa yang sejatinya dimiliki.
Menurut Debord, tidak ada jalan keluar untuk melepaskan diri dari masyarakat tontonan. Jika ingin melawan, satu-satunya cara adalah ikut bermain di dalamnya (detournament). Pemujaan terhadap gelar membuat orang berlomba-lomba mencari celah agar namanya bisa tampak menyandang gelar mentereng. Akibatnya, kampus-kampus ruko tumbuh menjadi penadah bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu mengakses stempel kampus bereputasi, namun memiliki sumber daya (baca: kemampuan ekonomi) yang berlebih.
Saya sempat menduga kampus-kampus bereputasi menyediakan ruang itu untuk melawan sistem dari dalam. Apalagi kampus memiliki kebutuhan materil, sehingga perlu ada sedikit kompromi antara idealisme kampus dengan kebutuhan pasar. Namun semakin 'ke sini' rasa-rasanya kondisinya semakin 'ke sana'. Kampus-kampus justru menikmati proses marketisasi dan berupaya mencari alibi agar tercipta ruang dan situasi berlanjut yang saling menguntungkan antara kampus dengan penguasa pasar.
Di titik ini, kekaguman saya pada sosok Pak Udin kian menemukan alasannya.
Sarjoko S mahasiswa Doktoral Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta