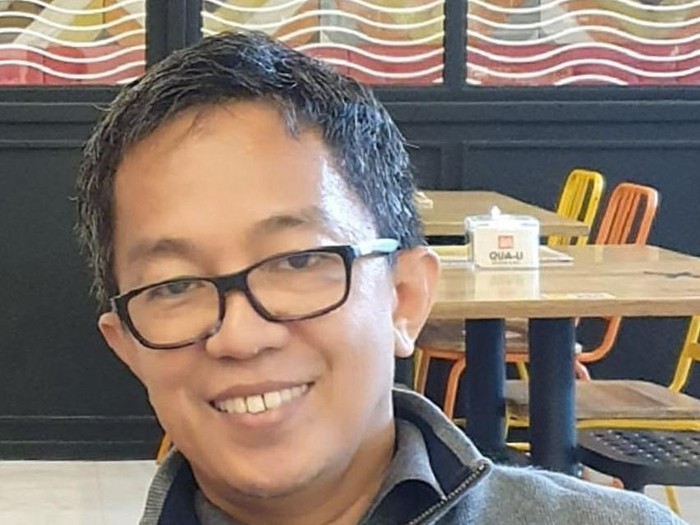Agustus kembali menyapa. Pertanda datang dan berseminya keriangan pesta di seantero negeri. Bangsa yang memanjatkan puji atas berkah yang dituai dengan epik heroisme luar biasa: Indonesia yang merdeka. Agustus selalu penuh romantisme.
Tidak hilang dan tak akan pernah hilang hingga ke ujung zaman. Canda ria beragam arena lomba antar warga adalah bait-bait puisi tentang harmoni dari mozaik tak berhingga warna. Indah tiada tara.
Merdeka adalah pembebasan untuk berlepas diri dari belenggu titik nol lalu bergerak maju menuju lini depan domain pencerahan peradaban. Tenteram dalam keyakinan dan kemampuan berkarya. Bahwa cerdas itu elok mencerdaskan. Laksana baiknya pengetahuan yang kuasa menyulap rahmat kekayaan alam dan keberagaman budaya menjadi pundi-pundi kesejahteraan. Merdeka itu memerdekakan. Sudah semestinya demikian bukan?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meretas Belenggu
Membincangkan pembebasan diri dan pelepasan ekspresi menggiring saya untuk menulis tentang tiga simpul yang bertaut dalam pemikiran saya hari ini. Yang pertama adalah tentang kreativitas berekspresi anak-anak muda di Citayam Fashion Week. Saya melihatnya sebagai manifesto pemberontakan yang genuine, jujur dan terbuka. Semacam kredo pemutus belenggu. Mereka menyindir angkuhnya
industri fashion yang mapan dan galmour dengan kreativitas spontan di ruang terbuka.
Perlawanan bernyali tanpa pikir panjang. Berayun dalam laju cepat gelombang perubahan yang mendisrupsi. Beresonansi dengan spirit budaya digital yang lalu menjadikan mereka bak pijar yang mengundang. Bertransfomasi layaknya bintang ternama bersuara merdu. Menyentuh kesadaran dengan godaan kuat dalam cara yang sangat tak biasa.
Anak-anak muda itu menorehkan definisi ekspresi merdeka dalam cara original mereka sendiri. Harus diakui bahwa itu berhasil. Menjadi magnet dan berdaya pikat. Pesohor bahkan politisi lalu memandang dan bertandang. Citayam fashion Week setidaknya menegaskan dua efek yang selalu hadir sebagai penyerta dari setiap ragam kreativitas original. Yang pertama tentu saja apresiasi dari mereka yang
merasa terinspirasi. Terpanggil untuk memberi penguatan yang menggenapi misi perlawanan mereka dalam aspek berbeda. Misal saja pada sisi bisnis dan kekayaan intelektualnya. Efek penyerta yang kedua berkait dengan pijar yang justru memantik kerakusan dari pihak yang diliputi hasrat culas dan kooptasi. Kedua efek itu merupakan wujud kebenaran hukum alam. Seperti laron yang terpikat cahaya.
Simpul kedua adalah tentang anak muda yang berhidmad menjadi professional unik. Dialah Marcel Radhival yang lebih dikenal dengan nama Pesulap Merah. Sosok yang kini tersohor karena nyalinya yang besar membongkar rahasia para dukun. Kanal Youtube-nya diikuti oleh lebih dari dua juta subscriber. Kehadirannya di kanal Podcast Deddy Corbuzier telah dilihat oleh hampir tiga juta orang hanya dalam waktu dua hari pasca tayang. Sang Pesulap melakukan perlawanan terhdap sesuatu yang ternilai sebagai bentuk pembodohan. Muslihat yang sengaja dikemas dengan simbol religi nan justru menjauhkan publik dari kebenaran dan hak berpengetahuan.
Seperti halnya para pemberontak kreatif di Citayam Fashion Week, tindakan Pesulap Merah juga merupakan ekspresi keunggulan berpengetahuan yang disajikan secara genuine. Menjadi sangat menarik diketahui bahwa ternyata semua perlawanannya adalah bagian dari hasrat mencerdaskan bangsa. Itulah esensi kredo pembebasan yang ia persembahkan bagi seluruh khalayak yang dipandangnya sebagai keluarga.
Berani melangkah untuk mengupas kungkungan belenggu asupan pemahaman keliru dan menipu.
Citayam Fashion Week dan Pesulap Merah adalah singkapan ayat semesta tentang daya juang dan kecakapan menciptakan solusi untuk meretas belenggu dalam cara yang ternilai tak lazim. Keberanian mengambil posisi berdiri dan bercara pandang yang tegas. Pemaknaan kebenaran yang hanya dapat dinikmati dengan kekuatan jiwa merdeka. Bahwa merdeka itu memang harus memerdekakan. Lantas apa simpul ketiganya?
Membangun Kultur Akademik Bahagia
Tak lain tentang ekspresi malu seorang professor seperti termuat di laman Kompas tanggal 6 Agustus 2022. Perasaan tak bahagia yang ditautkan dengan atmosfir dan ekosisitem riset para dosen dan profesor di tanah air. Bukan itu saja, sang Guru Besar bahkan secara berani mendefinsikan pengelompokan ragam dosen dan professor. Sajian pemikiran itu tentu saja memancing perhatian dan hasrat ingin tahu yang lebih jauh. Klasifikasi yang ditulisnya justru memunculkan pertanyaan.
Anda sendiri berada di kelompok yang mana dan telah berbuat apa? Pada keadaan seperti itu internet selalu memberi jalan kepada pengungkapan jawaban benderang. Google Scholar, Scopus, Sinta, Publons, ResearchGate, Academia, Impactio dan lain sebagainya adalah pintu besar yang dapat diketuk siapa saja.
Membaca fakta yang tertelusur nyata membuat saya maklum. Elok dan bijak baginya yang menyadang jabatan Guru Besar untuk mengakui perasaan malu. Nun menjadi sangat tak bijak jika kemudian apa pun keadaan ekosistem inovasi dan riset bangsa kita saat ini dikiaskan sebagai salah satu simpul sebab dari rasa malu para profesor.
Memang benar bahwa boleh dikata semua peneliti dan akademisi mendambakan sistem inovasi dan regulasi riset yang lebih membangkitkan gairah. Sistem hebat yang membebaskan dosen dan peneliti dari tekanan kesalahan administratif khususnya berkait pertanggungjawaban keuangan. Menjadi anugerah besar jika kemudian kelak pertangungjawaban riset cukup berwujud sajian bukti pencapaian kinerja. Atmosfir
berkreativitas yang tentu elok diperjuangkan dengan memeperkuat budaya akademik maju. Terbangun dengan itikad baik, berjalan dalam manajemen prasangka baik, dan terikat dalam kekuatan integritas yang juga baik.
Maka menjadi tak sepadan jika kemudian saya membandingkan suasana batin Sang Profesor di atas dengan kebahagiaan berkarya diaspora Indonesia Dr. Josaphat Tetuko Sri Sumantyo yang menjadi professor di Chiba University. Atau dengan Dr. Rizal Fajar Hariadi yang juga menjabat professor di Arizona State University (ASU).
Mereka adalah sosok yang selalu diliputi gairah dan energi menjawab tantangan berkarya dengan perasaan bahagia. Bangga atas apa yang telah dilakukan dan diberikan universitasnya kepada kemerdekaan berkarya mereka.
Ekosistem riset di universitas kita memang belum sehebat di Chiba University maupun ASU. Namun tidak semua dosen di Indonesia sedemikian tak bahagia. Begitu banyak sosok yang secara luar biasa mampu secara kreatif menghadirkan lompatan dan solusi hebat meski dalam keadaan yang bagi sebagian orang terasa sebagai rintangan. Sejawat saya Muhammad Nizam, Agus Purwanto dan Wahyudi Sutopo adalah contoh karakter yang sangat bahagia berkarya. Ketiganya adalah professor yang merintis, membangun dan membesarkan unit riset dan pengembangan batere di Universitas Sebelas Maret. Tentu dan pasti banyak contoh kisah bahagia yang serupa di universitas lain.
Lalu apakah para dosen dan professor di universitas kita tidak memiliki kredo pembebasan yang serupa dengan anak-anak muda di Citayam maupun Sang Pesulap Merah?
Kredo itu pasti ada. Setiap dosen dan professor hanya perlu mengajukan pertanyaan kecil kepada diri mereka sendiri. Mengapa seorang professor harus menjadi professor (sebenarnya)? Setiap ilmuwan hanya perlu mendefinisikan tantangan yang elok mereka taklukkan. Mengambil posisi berdiri yang tegas sembari menorehkan bukti kecil tertelusur. Bahwa terdapat tipak penanda bernilainya daya sajian pengetahuan, solusi dan hikmah yang tersemat pada diri dan institusi mereka.
Mungkin begitulah seharusnya cara bekerja ilmuwan merdeka.
Iwan Yahya. Dosen dan Peneliti. The Iwany Acoustics Research Group (iARG) Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta.