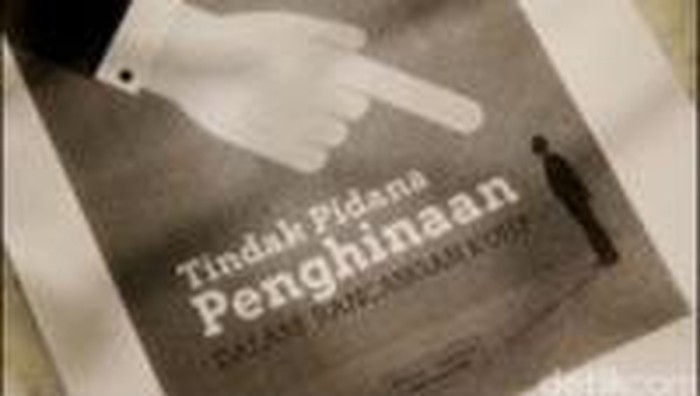Pasal penghinaan presiden kembali dihidupkan dalam RKUHP yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK No.013-022/PUU-IV/2006. Banyak yang khawatir pasal ini akan digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Namun, Wakil Menteri Hukum dan Ham Prof. Eddy O.S Hariej menegaskan bahwa Pasal penghinaan presiden di RKUHP adalah delik aduan, bukan delik biasa yang dibatalkan MK.
"Mengapa kita tetap mempertahankan pasal penghinaan kepada presiden? Simpel saja. Kita buka semua KUHP di semua negara di dunia ini, pasti ada bab yang berjudul 'kejahatan yang melanggar terhadap martabat kepala negara asing'. Simpelnya begini. Kalau kepala negara asing saja martabatnya dilindungi, masak kepala negara sendiri martabatnya tidak dilindungi?" demikian ucapan Wamenkumham Prof. Eddy O.S Hariej (detikcom, 9/4).
Menjadi kontroversial karena pasal penghinaan presiden di RKUHP beririsan langsung dengan kebebasan berpendapat yang merupakan hak konstitusional warga negara (Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945). Yang dalam konteks pidana sangat erat kaitannya dengan asas cogitationis poenam nemo patitur, pikiran dan pendapat berada di luar jangkauan pidana. Atau di ranah peradilan kita mengenalnya dengan istilah audi et alteram partem, sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya dengarkan sisi lain.
"Mengapa kita tetap mempertahankan pasal penghinaan kepada presiden? Simpel saja. Kita buka semua KUHP di semua negara di dunia ini, pasti ada bab yang berjudul 'kejahatan yang melanggar terhadap martabat kepala negara asing'. Simpelnya begini. Kalau kepala negara asing saja martabatnya dilindungi, masak kepala negara sendiri martabatnya tidak dilindungi?" demikian ucapan Wamenkumham Prof. Eddy O.S Hariej (detikcom, 9/4).
Menjadi kontroversial karena pasal penghinaan presiden di RKUHP beririsan langsung dengan kebebasan berpendapat yang merupakan hak konstitusional warga negara (Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945). Yang dalam konteks pidana sangat erat kaitannya dengan asas cogitationis poenam nemo patitur, pikiran dan pendapat berada di luar jangkauan pidana. Atau di ranah peradilan kita mengenalnya dengan istilah audi et alteram partem, sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya dengarkan sisi lain.
Di samping itu juga dibatasi oleh Konstitusi itu sendiri untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28 J ayat (2) UUD 1956). Dalam konteks penghinaan presiden, pembatasan kebebasan berpendapat itu dikualifikasi sebagai penghinaan apabila diekspresikan dalam bentuk suatu pernyataan permusuhan yang menimbulkan kebencian dan bersifat merendahkan sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.71K/Kr/1973.
Sedangkan alasan penghidupan kembali pasal penghinaan presiden di RKUHP dapat dibenarkan secara hukum, sepanjang terdapat paradigma hukum baru seperti pasal itu delik aduan, bukan delik biasa yang dimatikan MK. Contoh alasan hukum ini terdapat pada Putusan MK No.003/PUU-IV/2006 terhadap Pengujian Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang ditetapkan sebagai delik formil. Kemudian pada Putusan MK 25/PUU-XIV/2016 dirubah menjadi delik materiil dengan adanya paradigma hukum baru pasca berlakunya UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Terlepas dari persoalan tersebut, destinata tantum pro factis non habentur yang berarti maksud baik tidak serta-merta diikuti dengan tindakan yang baik. Adagium ini cukup pas untuk menggambarkan keberadaan pasal penghinaan dengan banyaknya kasus para pengkritik kebijakan pemerintah yang dikriminalisasi. Ironisnya, posisinya bukan presiden langsung yang mengadukan, melainkan para pendukung atau orang-orang di sekitar presiden. Kemudian direspons aparat penegak hukum yang cenderung berlebihan dan represif. Itulah kekeliruan terbesar dan nyata dalam penegakan hukum pasal penghinaan terhadap pengkritik kebijakan pemerintah.
Sedangkan di sisi lain, tidak bisa dinafikan pula banyak yang mengekspresikan kebebasan berpendapatnya secara kebablasan untuk menyinggung, menuduh, dan menyerang harkat dan martabat orang lain yang belum jelas juntrungannya. Lalu bermain layaknya korban (playing victim) seperti contoh dalam kasus gugatan pencemaran nama baik antara Johnny Depp, bintang Pirates of the Caribbean melawan mantan istrinya Amber Heard.
Rumusan yang jelas dan tegas
Poltaris menukilkan: Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi pada saat diundangkan, undang-undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan tak terpikirkan pada saat dan pembahasan rumusan'.
Setiap UU selalu menyisakan masalah. Kekakuan formalitas, rumusan yang samar-samar, dan tidak tegas, bahkan multi-tafsir. Inilah pintu masuk bagi kekuasaan kehakiman sebagai cabang trias politica untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman). Meskipun pembentukan hukum melalui Putusan hakim (judge made law) sangat erat dengan praktik hukum common law.
Tetapi menurut Lie Oen Hock, hakim melalui peradilan dapat menetapkan sendiri makna ketentuan UU yang tidak jelas dalam suatu UU dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan UU secara gramatikal atau historis, baik recht maupun wetshistoris. Setidaknya, Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang menjadi landmark decision dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam membangun konstruktivisme hukum pasal penghinaan presiden yang progresif dan berkeadilan.
Putusan MA yang telah sesuai dengan kaidah hukum acara pidana dan telah memposisikan perlindungan kebebasan berekspresi pada posisinya di antaranya; pertama, konsekuensi pasal penghinaan presiden sebagai delik aduan (klacth delicten), maka yang punya legal standing sebagai pengadu adalah:
(1) perseorangan (persoonlijk) yang punya perasaan dan kepribadian (personality), bukan badan hukum (rechtpersoon), badan publik (openbaar lichaam), atau jabatan (ambt) yang tidak punya perasaan dan kepribadian.
(2) wajib korban langsung dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, kecuali di bawah umur. Kaidah hukum ini ada di Putusan Pengadilan Negeri Bantul No.196/Pid.Sus/2014/PN.BTL yang menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik adalah delik aduan absolut yang boleh melaporkan adalah korban langsung.
Hanya saja, penggunaan istilah ''presiden dan wakil presiden'' dalam pasal penghinaan presiden di RKUHP masih mendeskripsikan jabatan (ambt), bukan personal. Dalam hukum administrasi negara misalnya, seorang presiden dan wakil presiden berkedudukan sebagai personal apabila mengajukan cuti dan sedang tidak melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu.
Lalu, kapan seorang presiden dan wakil presiden berkedudukan sebagai personal dalam hukum pidana? Inilah lubang hukum (loop hole) yang harus ditutup para legislator. Sebab, dalam konteks pertanggungjawaban jabatan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.572 K/Pid/2003, maka pernyataan atau pendapat atas suatu kebijakan atau jabatan harusnya dimaknai sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal.
Kedua, sifat melawan hukum delik pasal penghinaan presiden harus dirumuskan secara jelas (lex certa) dan tegas tanpa analogi (lex stricta) terutama terkait konten dan konteks. Dalam suatu konten harus ada penyebutan nama langsung. Sedangkan konteks berperan memverifikasi suatu kandungan atas konten termasuk menghina atau tidak. Kaidah hukum ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 292/Pid.B/2014/PN.Rbi yang menegaskan dalam penghinaan penting adanya: (1) penyebutan nama langsung dan (2) adanya tuduhan.
Sedangkan untuk tuduhan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.30 K/Kr/1969, setiap tuduhan tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum. Rumusan sifat melawan hukum dari suatu pendapat atau percakapan inilah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai dan kepatutan dalam masyarakat demokratis sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.275 K/Pid/1983.
Acuan untuk sifat melawan hukum dari penghinaan dapat merujuk pada Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, yaitu (1) melanggar hak orang lain, (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (3) bertentangan dengan kesusilaan, dan (4) bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
Yang ditambah dengan adanya pencelaan dari masyarakat sebagai penyempurnaan rumusan delik penghinaan presiden yang lebih elaboratif dalam bentuk: (1) tanpa hak, (2) mengetahui hal-hal yang pantas, tapi tidak berusaha mencegahnya, (3) tidak sesuai dengan kebenaran dan fakta yang sebenarnya, dan (4) melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan yang menyinggung kehormatan dan kehidupan pribadi seseorang sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.71K/Kr/1973 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 027K/SIP/1972 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1265 K/Pdt/1984.
Ketiga, adanya pengecualian sebagai alasan penghapusan pidana. Seperti (1) demi kepentingan umum, (2) terpaksa membela diri, (3) objeknya seorang pejabat yang dituduh dalam melaksanakan tugasnya, (4) sesuai dengan kebenaran dan fakta yang sebenarnya, dan (5) pelaku telah meminta maaf dan adanya maaf dari korban. dan/atau secara analog berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata dengan pertimbangan: (1) kasar atau tidaknya penghinaan dan (2) pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak. Sehingga alasan-alasan tersebutlah yang menjadi alasan pembenar yang sifatnya menghapuskan pidana (negative materielle weterrechtelijk) pada pasal penghinaan presiden sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.338/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst jo. Putusan PN Tangerang No.1269/PID.B/2009/PN.TNG.
Keempat, pelaksanaannya sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) yang merupakan bungkusan terluar dalam penegakan hukum. Upaya Hukum lain seperti gugatan perdata yang bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan kehormatan dan nama baik (Pasal 1372 KUHPerdata) harus dikedepankan dalam penyelesaian kasus. Sebagai komparasi, dalam wet administratiefrechtleijke handhaving verkeersvoorschriften (UU Lalu Lintas yang menggunakan penegakan hukum administrasi) atau lex mulder sesuai dengan pembuatnya Prof. A. Mudler yang mengubah cara penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas sepanjang tidak menyebabkan luka atau kerugian harta benda dengan menggunakan pendekatan koreksi dan prosedur hukum administrasi.
Dari segi tujuan, penggunaan prosedur perdata atau administrasi dalam penyelesaian kasus penghinaan presiden sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Putusan Mahkamah Agung No.39 PK/Pid.Sus/2011 adalah edukatif, korektif, dan preventif. Apalagi secara prosedural proses peradilan perdata yang harus didahului dengan mediasi dan konstruksi Pasal 1374 KUHPerdata, dimana pelaku dimuka umum di hadapan hakim dapat mencegah dikabulkannya tuntutan dengan cara: (1) meminta maaf, (2) menyesali perbuatannya, dan (3) menyatakan orang yang dihina itu adalah orang terhormat untuk menciptakan perdamaian.
Sebagaimana adagium het recht der wekelijkden (Putusan Pengadilan yang sesuai dengan kesadaran, kebutuhan hukum, dan nilai-nilai keadilan masyarakatlah hukum dalam makna yang sebenarnya). Maka pembangunan hukum lewat pembaruan hukum yang bersumber dari putusan-putusan pengadilan merupakan cerminan dalam membangun hukum yang lebih progresif (baca: hukum progresif) yang menempatkan keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan dan menunjukkan bahwa hukum itu dibentuk memang untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
Agung Hermansyah dan Arif Sastra Wijaya advokat, konsultan, dan peneliti hukum di Jakarta
(mmu/mmu)