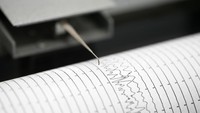Urbanisasi telah banyak mengubah wajah Indonesia, Di masa awal kemerdekaannya, proporsi penduduk yang hidup di perkotaan hanya 10 persen. Saat ini telah mencapai 56 persen, dan 25 tahun mendatang diproyeksikan sebesar 70 persen. Inheren dengan proporsi ini, tingkat kesejahteraan dan standar hidup layak di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan, Indonesia memasuki era perkotaan (urban age).
Namun, ada paradoks yang muncul di balik catatan-catatan tersebut. Kesenjangan pembangunan terjadi antarwilayah. Wilayah Jawa mengalami tingkat urbanisasi paling tinggi. Untuk indikator ekonomi, wilayah tersebut mendominasi pertumbuhan ekonomi nasional hingga 59 persen (BPS, 2019). Sementara indikator demografi, wilayah tersebut memiliki proporsi konsentrasi penduduk mencapai 56,56 persen. Kesenjangan lainnya tampak pada disparitas tinggi penduduk miskin kota dan non-kota.
Pada 2017, terdapat 17,1 juta orang miskin di daerah non-kota, sementara di daerah kota 10,6 juta orang. Ini menunjukkan kondisi pembangunan tidak merata yang tinggi dalam pola urbanisasi di Indonesia; suatu perkembangan yang pesat dalam lingkup wilayah yang kecil dibarengi keterbelakangan perkembangan pada lingkup wilayah lain yang lebih luas. Di tengah situasi ini, perkembangan pariwisata dalam beberapa waktu terakhir memberikan garansi dalam mengatasi kebuntuan urbanisasi dengan menginisiasi pola baru urbanisasi di Indonesia yang berorientasi pada agenda pemerataan pembangunan di Indonesia.
Trayektori Kepariwisataan
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Industri pariwisata di Indonesia dapat dilacak sejak akhir tahun 1960-an. Ketika itu, pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional, tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pemerintah kemudian merumuskannya ke dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I sampai V. Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kepariwisataan baru dikeluarkan pada 1990 melalui Undang-undang No. 9 tahun 1990. Ini terjadi karena, pada saat itu kebijakan politik pemerintah menempatkan industri pariwisata sebagai sektor utama untuk meningkatkan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi.
Meski telah dimulai sejak tahun 1960-an, dampak industri pariwisata bagi pembangunan nasional belum menunjukkan hasil signifikan. Persepsi masyarakat yang melihat pariwisata secara negatif menjadi pemicu utama. Pariwisata cenderung diasosiasikan dengan aktivitas yang melanggar norma-norma kesusilaan dan merusak kebudayaan. Banyak tokoh agama dan pemuka masyarakat tidak berpihak kepada pembangunan pariwisata karena persepsi demikian. Ditambah lagi, informasi yang utuh tentang pariwisata masih sangat terbatas diterima oleh masyarakat. Pemicu lainnya, kehadiran industri pariwisata di masa-masa awal yang cenderung berorientasi pada penerimaan devisa negara menyebabkan masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat secara riil.
Dalam perkembangannya, terjadi reorientasi arah pengembangan industri pariwisata dengan berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan mempersiapkan lapangan kerja untuk masyarakat. Undang-undang No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan yang tidak mempertimbangkan aspek manfaat riil untuk masyarakat kemudian direvisi, lalu melahirkan UU No. 10 tahun 2009. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 menyebut kepariwisataan sebagai salah satu ujung tombak perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ardika, 2019).
Persepsi negatif masyarakat tentang pariwisata perlahan berubah karena sosialisasi yang terus dilakukan dan penyebaran informasi yang utuh tentang pariwisata. Manfaat riil yang dirasakan masyarakat menjadi alasan lain berubahnya persepsi ini. Pada 2011, Kepariwisataan berkembang di banyak daerah di Indonesia. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), Indonesia menetapkan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang tersebar di banyak daerah.
Manfaat pariwisata bagi pembangunan nasional baru menunjukkan hasil signifikan sejak 2015. Pemerintah menjadikan pariwisata sebagai leading sector pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (Kemenpar, 2018). Untuk mencapai tujuan ini, pengembangan pariwisata dilakukan melalui pemetaan pelanggan/wisatawan dan penentuan jenis destinasi wisata; penyediaan akses baik akses data, akses pembiayaan, maupun akses/konektivitas antardaerah; dan perkuatan amenitas mendukung kebutuhan wisatawan di daerah wisata.
Strategi pengembangan ini melibatkan banyak aktor, yaitu akademisi sebagai konseptor, pemerintah sebagai regulator, swasta sebagai eksekutor, media sebagai katalisator, dan komunitas masyarakat sebagai akselerator. Strategi dan kolaborasi ini menghasilkan percepatan pembangunan sektor pariwisata hanya dalam waktu singkat. Indonesia menurut World Travel and Tourism Council (WTTC) berada di peringkat 9 dunia dalam hal perkembangan pariwisatanya. Bahkan untuk Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara yang paling cepat pertumbuhan pariwisatanya. Dan, sejak 2018 sektor pariwisata menempati urutan pertama dalam menyumbang devisa bagi negara, setelah pada 2015 menempati urutan keempat.
Menjawab Kebuntuan
Pengembangan kepariwisataan Indonesia memberi jawaban atas kebuntuan urbanisasi hari ini, kemudian menginisiasi perjalanan urbanisasi di Indonesia ke depannya. Jawaban atas kebuntuan urbanisasi hari ini ditelaah dari pergeseran paradigma kepariwisataan, strategi pengembangan pariwisata, dan pola pengelolaan kepariwisataan.
Dari aspek paradigma, menempatkan pariwisata sebagai industri semata menjadikan kepariwisataan sebagai hal yang eksklusif dimiliki oleh para pemodal dan penguasa. Sedangkan, masyarakat hanya menjadi objek yang dilibatkan untuk kepentingan penguasa (penerimaan devisa) dan pemodal (keuntungan ekonomi). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah pertumbuhan dalam tataran makro, sementara manfaat riil yang dirasakan oleh masyarakat, tidak tercapai. Paradigma inilah yang menjadikan pariwisata Indonesia di tahun 1960-an sampai 1990-an tidak berkembang signifikan, selain alasan persepsi masyarakat tentang pariwisata.
Memasuki abad ke-21, wacana pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menjadi pembahasan negara-negara di dunia turut mempengaruhi paradigma kepariwisataan. Pariwisata tidak lagi dilihat hanya sebagai industri yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi mencakup peningkatan kualitas manusia secara holistik. Dengan paradigma baru ini, pariwisata menjadi instrumen yang mewujudkan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan secara bersamaan. Sifatnya menjadi inklusif dengan peran masyarakat sebagai subyek yang memberdayakan dirinya sendiri melalui pariwisata.
Karena perluasan paradigma ini, strategi pengembangan pariwisata pun ikut berubah. Pemerintah dan swasta tidak lagi dominan dalam mengembangkan sektor pariwisata. Keterlibatan para akademisi, komunitas masyarakat, dan media massa sangat penting untuk memastikan kemanfaatan pariwisata secara holistik. Pemerintah dengan fungsinya sebagai pengatur tidak bisa otoriter untuk mengarahkan pariwisata hanya menguntungkan pihaknya, begitu pun pihak swasta tidak bisa sebebasnya mengambil keuntungan dari pariwisata tanpa memperhatikan batasan-batasan daya dukung alam.
Sebaliknya, masyarakat menjadi lebih leluasa untuk mendatangkan manfaat ekonomi dan sosial dari aktivitas pariwisata. Dan terakhir, untuk memastikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, peran akademisi untuk melakukan kajian dan perencanaan, serta peran media massa sebagai kontrol dan katalisator aktivitas pariwisata menjadi sangat urgen.
Pariwisata sebagai instrumen pembangunan nasional yang bersifat inklusif menyediakan peluang terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Satu wujud konkretnya hari ini adalah munculnya pariwisata perdesaan yang model pengelolaannya dilakukan melalui pariwisata berbasis komunitas (Community Based Tourism). Berkembangnya model kepariwisataan desa ini diidentifikasi melalui dua hal. Pertama, wacana pembangunan berkelanjutan yang menempatkan orientasi sosial dan kelestarian lingkungan sama pentingnya dengan orientasi ekonomi dalam pembangunan.
Desa sebagai hunian manusia memiliki warisan nilai-nilai sosial yang masih terjaga dengan baik. Selain itu, desa masih mempertahankan lingkungan alamnya yang tidak tersentuh oleh dampak negatif modernisasi. Dengan dua kondisi ini, desa menjadi role model dan memiliki posisi tawar penting dalam agenda paradigma pembangunan berkelanjutan.
Kedua, paradigma pembangunan berkelanjutan turut mempengaruhi preferensi masyarakat global dalam bidang pariwisata. Saat ini, berkembang tren pariwisata dunia yang mengarah kepada demasifikasi atau fragmentasi pasar. Tren ini disebabkan oleh bergesernya preferensi wisatawan untuk memilih produk-produk wisata yang menekankan unsur pengalaman, keunikan, dan kualitas. Desa memiliki semuanya itu, keunikan pengalaman sosial-budya dan keindahan alam yang masih terjaga.
Dengan adanya tren demikian, peluang peningkatan ekonomi masyarakat menjadi besar dan pemerataan pembangunan dapat terwujud, karena masyarakat menjadi aktor utama dalam mengembangkan pariwisata di desa. Dua contoh wisata perdesaan yang saat ini berkembang di Indonesia adalah Desa Wisata Pentingsari (Yogyakarta) dan Desa Wisata Nyegara Gunung (Bali).
Melalui pengelolaan kepariwisataan desa berbasis komunitas, desa menjadi lokus bertumbuhnya faktor produksi dan peluang usaha yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Lapangan-lapangan pekerjaan mulai bertumbuh di desa. Tenaga kerja terampil yang dimiliki oleh desa dapat mengisi lapangan pekerjaan ini. Dengan demikian, manfaat ekonomi secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika 74 ribu desa di Indonesia yang memiliki keunikan lanskap dan budaya masing-masing memanfaatkannya untuk kepariwisataan desa, dampaknya akan sangat signifikan bagi pemerataan pembangunan. Sehingga, di satu sisi migrasi desa ke kota akan menurun dengan signifikan, di sisi lain infrastruktur ekonomi dan suprastruktur sosial-budaya daerah perdesaan akan terbangun dan menunjukkan ciri-ciri perkotaan.
Selain itu, berkembangnya kota-kota wisata di Indonesia sebagai implikasi ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dapat berkontribusi terhadap tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di Indonesia. Pengembangan kota-kota wisata yang menjadikannya sebagai pusat-pusat ekonomi baru di Indonesia dapat dilakukan melalui kemitraan publik dan swasta.
Sektor publik yaitu pemerintah kota memiliki peran kunci dalam mengembangkan strategi pariwisata, menyediakan dan mengelola ruang terbuka publik, membangun dan memelihara produk budaya dan alam untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, serta memberikan hibah untuk menopang sektor swasta. Sedangkan sektor swasta memiliki peran dalam perencanaan, manajemen, dan pemasaran pariwisata di kota.
Kemitraan publik dan swasta dalam mengembangkan wisata kota berimplikasi terhadap perkembangan infrastruktur ekonomi dan suprastruktur sosial-budaya kota-kota tersebut. Kota kecil, sedang, bahkan daerah urban baru yang mengembangkan kota wisata akan menjadi pusat ekonomi aglomerasi baru yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Konsentrasi penduduk tidak lagi hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menyasar pada daerah-daerah pertumbuhan ekonomi baru dari aktivitas pariwisata. Migrasi dari desa ke kota akan menyasar daerah-daerah baru ini, sehingga meminimalisir migrasi masuk ke kota-kota besar di Indonesia.
Agenda Studi ke Depan
Kepariwasataan dan urbanisasi adalah perpaduan yang relatif baru dalam diskursus pembangunan; setidaknya itu yang terjadi di Indonesia. Pertautan antara keduanya menghasilkan pola baru dalam urbanisasi sekaligus memberi jawaban atas tantangan pemerataan pembangunan. Daerah-daerah yang memiliki potensi besar di bidang pariwisata menjadi pusat-pusat aktivitas ekonomi, politik, sosial-budaya, dan modernisasi. Urbanisasi berlangsung seiring berkembangnya daerah-daerah tersebut sebagai pusat aktivitas manusia. Pola urbanisasi mulai berubah, tidak lagi hanya terkonsentrasi pada kota-kota besar yang merupakan pusat industrialisasi, melainkan berkembang dan menyebar ke daerah-daerah pariwisata.
Kajian tentang urbanisasi yang dipicu oleh pariwisata penting untuk dilakukan di Indonesia ke depannya, mengingat kepariwisataan menjadi leading sector pembangunan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian-penelitian serupa telah banyak di lakukan di negara lain, seperti di Australia yang dilakukan oleh Mullins (1994) terhadap kota Gold Coast dan Sunshine Coast dan di China yang dilakukan oleh Junxi Qian, Dan Feng, Hong dan Zhu terhadap kota Zhapo. Kedua penelitian ini sama-sama mengafirmasi tesis tentang urbanisasi pariwisata (tourism urbanization) sebagai penciptaan ruang-ruang konsumsi pada kota (kota yang dibangun untuk tujuan kesenangan).
Namun, terdapat perbedaan dalam satu hal dari kedua penelitian ini. Mullins melihat urbanisasi pariwisata pada kota Gold Coast dan Sunshine Coast adalah produk dari post-modern, sementara urbanisasi pariwisata kota Zhapo dibentuk oeh modernisasi di China. Kajian tentang urbanisasi pariwisata untuk kota-kota baru di Indonesia ke depan bertujuan untuk menelaah karakteristik tertentu dari bentuk urbanisasi pariwisata tersebut, dan diharapkan memberikan sumbangan besar bagi perkembangan urbanisasi dan wacana pemerataan pembangunan di Indonesia.
Alfred Nabal, M.Si, Pascasarjana Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia
Simak juga 'Menuju RI Bebas Karantina, Menparekraf Ingatkan Pelaku Pariwisata Hal Ini':