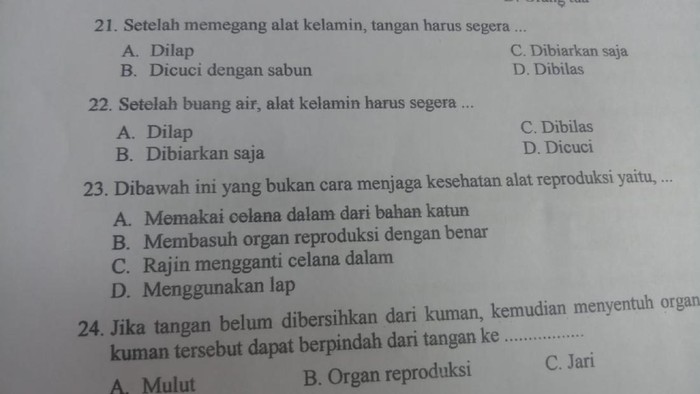Selama mengajar di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di sebuah universitas swasta di Palembang, saya menyadari ada kesalahan dalam penyusunan soal ujian. Mulai dari soal yang tidak sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, ketiadaan konteks, hingga soal yang salah secara logika.
Fakta tersebut saya temukan dalam proses perkuliahan di beberapa mata kuliah terkait perencanaan pembelajaran di sekolah dasar yang saya ampu. Sebagaimana nama mata kuliahnya, tujuan akhir perkuliahan adalah mahasiswa mampu merancang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tersebut dilengkapi dengan soal ujian atau evaluasi.
Dalam proses perkuliahan, saya mempelajari pola yang diterapkan mahasiswa dalam menyusun soal yang akan digunakan untuk menguji pemahaman peserta didik. Meski mahasiswa berganti setiap semester (kecuali yang mengulang tentu saja), penyusunan soal ternyata kurang lebih sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mula-mula mahasiswa menyajikan teks. Pertanyaan yang diajukan kemudian menggali pemahaman teks tersebut. Kemudian nilai ditentukan berdasarkan jawaban benar terhadap soal pemahaman dasar tersebut. Misalnya, mahasiswa menyajikan kutipan cerita pendek. Mahasiswa menyusun soal hanya sebatas pada siapa tokoh dalam kutipan tersebut, latar yang digunakan, dan soal semacam itu.
Tentu itu tidak salah. Masalahnya, pola itu hanya menjadikan soal berhenti pada pertanyaan permukaan. Mahasiswa menyusun soal dengan tujuan menguji ingatan peserta didik terhadap teks saja. Padahal sebelum diminta menyusun soal ujian, mahasiswa mempelajari syarat soal. Salah satunya, soal diharapkan mampu mengakomodasi kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan menggunakan dan mengolah proses berpikir di atas fakta. Melalui soal yang disajikan, peserta didik tidak hanya mengetahui fakta tertentu tetapi menggunakan pengetahuannya untuk mengembangkan pengetahuan itu sendiri.
Tentu saja soal dengan pola 5W (what, who, when, why, where) boleh disajikan sebagai pengantar. Maksudnya, peserta didik mengumpulkan informasi dasar dengan menjawab pertanyaan tersebut. Namun, pendidik (dalam hal ini mahasiswa) perlu menambahkan soal lain. Soal yang dimaksud adalah soal yang mengembangkan pengetahuan peserta didik dengan menggunakan informasi dasar yang telah dikumpulkannya tadi.
Sebagai contoh, pendidik menyajikan teks kutipan cerita pendek. Mulanya, peserta didik diminta mengidentifikasi hal dasar dalam teks tersebut. Misalnya, tokoh dan konflik dalam kutipan tersebut. Soal lanjutan yang bisa disajikan adalah meminta peserta didik mencari informasi terkait konflik di media massa yang serupa dengan konflik dalam kutipan cerita pendek. Peserta didik diajak mendiskusikan konflik tersebut.
Diskusi yang dilakukan tidak hanya sekadar menemukan persamaan konflik saja. Peserta didik diajak juga untuk mengemukakan gagasannya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Gagasan itu harus dilandasi fakta dan pengetahuan lain. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik dapat ditingkatkan.
Temuan pola pembuatan soal pada mata kuliah perencanaan pembelajaran ini sejalan dengan temuan penelitian di sekolah dasar. Berdasarkan penelitian yang saya dan tim lakukan, kami menemukan soal-soal yang masih berada pada tahap mengingat konsep atau mengumpulkan informasi dasar.
Pelatihan penyusunan soal tentu saja telah banyak dilakukan. Meski tentu saja kita tidak bisa mengharapkan seluruh wilayah di Indonesia mendapatkan hal yang sama.
Pendidik bukannya tidak memahami tuntutan soal yang mengakomodasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ada hal lain yang mendasari soal yang diberikan hanya ditahap ingatan saja. Salah satunya adalah jumlah materi yang cukup banyak. Diskusi tentang hal ini tentu saja nantinya akan berkesinambungan dengan banyak hal. Misalnya, fokus pembelajaran kita rata-rata memang masih pada tahap menyelesaikan materi dan bukan pada pemahaman materi.
Terlepas dari itu, jika soal yang disajikan di sekolah tidak ditingkatkan, tidak heran kita menemukan orang-orang yang belum mampu menghubungkan fakta. Tak hanya itu, kemampuan memecahkan masalah juga menjadi rendah. Dampaknya, ketika terjadi silang pendapat, kita menemukan banyak orang yang tidak mampu berpikir logis.
Debat yang dilakukan tidak lagi menyentuh hal yang substansi. Yang ada, orang kemudian menyerang personal bahkan membawa hal-hal yang tidak relevan seperti latar belakang keluarga, gender, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika ada diskusi terkait kasus pelecehan seksual di dunia pendidikan. Ada begitu banyak reaksi masyarakat. Kita bisa menemukan dengan mudah orang yang secara ringan menuding satu pihak sebagai pihak yang bersalah.
Diskusi kemudian berubah menjadi debat. Debat tersebut kemudian hanya berputar-putar pada siapa yang salah dan siapa yang benar. Padahal pada kasus semacam itu, kita butuh solusi nyata dan berpihak pada korban. Pertanyaannya, apakah debat kusir semacam ini muaranya hanya dari bidang pendidikan? Tentu saja pendidikan (salah satunya melalui penyajian soal) memang menyumbang kemampuan berpikir masyarakat kita. Namun, ini tanggung jawab kita bersama.
Untuk mengurai benang kusut persoalan semacam ini tentu dibutuhkan kerja sama banyak pihak. Setidaknya, dimulai dari komitmen meningkatkan kemampuan mahasiswa calon guru, baik dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi maupun dalam menyusun soal yang mengukur kemampuan tersebut.
Katarina Retno dosen PGSD
(mmu/mmu)