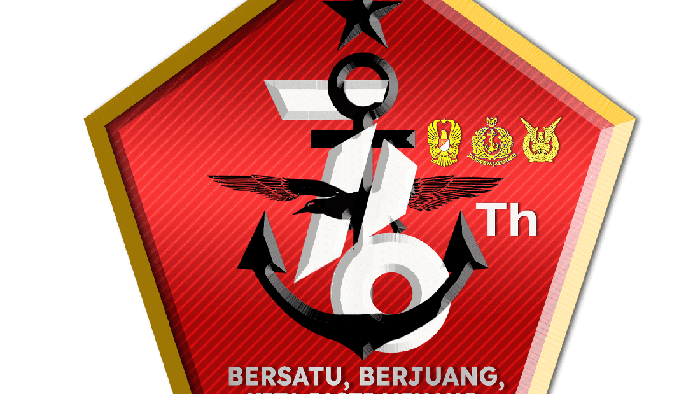Tema peringatan HUT TNI 5 Oktober 2021 yakni "bersatu, berjuang, kita pasti menang" menegaskan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Begitu pula dengan slogan sebelumnya seperti "bersama rakyat, TNI kuat".
Namun, rakyat masih diposisikan sebagai mitra dan objek TNI dalam pelaksanaan tugas pokok. Padahal, potensi rakyat masih dapat dioptimalkan lebih dari pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI yang dijabarkan dalam Pasal 7 UU TNI. Rakyat juga dapat diajak bahu-membahu dalam pembangunan postur pertahanan, khususnya dalam pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan alutsista (alat utama sistem senjata) TNI. Hal itu karena di satu sisi postur TNI masih jauh dari ideal, khususnya ketersediaan dan kesiapan alutsista, sementara di sisi lain kemampuan APBN sangat terbatas.
Potret postur TNI yang belum ideal terlihat pada The Military Balance 2021 yang merupakan kajian tahunan lembaga riset pertahanan The International Institute for Strategic Studies (IISS) berbasis di London. Tingkat operasional pesawat tempur TNI AU misalnya, disebut 45 persen. Tingkat kesiapan tersebut tidak meningkat dibanding penilaian IISS yang dirilis pada The Military Balance 2012 yang juga 45 persen. Padahal, dalam rentang hampir sepuluh tahun itu jumlah personil TNI AU telah meningkat dari 24 ribu menjadi 30.100 orang, dan komando operasi AU telah bertambah dari dua menjadi tiga komando operasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya, rujukan dalam pembangunan postur pertahanan dan TNI lebih merujuk sumber tidak kredibel, seperti situs Global Fire Power (GFP). Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 Lampiran I hal. IV-105 tertera nilai indeks kekuatan militer yang semakin kecil berarti semakin bagus kekuatan tempurnya menurut metode GFP. Tahun 2019 sebagai baseline (posisi awal) mencapai 0,28. Lalu membaik tahun 2021 menjadi 0,25, dan tahun 2024 ditargetkan menjadi 0,2.
Sekalipun dalam RKP tidak disebut GFP sebagai sumber secara eksplisit, tapi pada Lampiran Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, 16 Agustus 2021, Global Fire Power disebut jelas sebagai rujukan. Padahal, GFP memiliki kebijakan disclaimer, yakni material dari seluruh situs tersaji untuk kepentingan historis dan hiburan (entertainment value).
Ketidakakuratan GFP misalnya terlihat pada penilaian kekuatan armada kapal (navy fleet strength). GFP hanya menilai berdasarkan jumlah kapal perang permukaan dan selam tanpa meneliti perbedaan ukuran dan kapabilitas kapal perang, kesiapan layar dan tempur kapal, termasuk dukungan logistiknya. Akibatnya, dalam aspek kekuatan armada kapal, Korea Utara yang disebut mempunyai 492 kapal berada di peringkat ketiga dunia mengalahkan Amerika Serikat (AS) yang "hanya" memiliki 490 kapal.
Padahal, dengan melihat lalu lintas kapal perang dan penjaga pantai AS, termasuk kapal induknya, di seantero lautan, dan sebaliknya hampir tak terlihatnya kapal perang Korea Utara beroperasi jauh di luar laut teritorialnya, kita dapat memastikan ketidakakuratan metode penilaian dan data terbaru GFP.
Dampak dari pemakaian nilai GFP adalah kesalahan penilaian postur pertahanan Indonesia, utamanya dari kementerian dan lembaga di luar Kementerian Pertahanan dan TNI. Pengadaan alutsista yang kredibel akan dinilai tidak mendesak, padahal sejak pembangunan postur pertahanan berbasis kekuatan pokok minimal (minimum essential force/ MEF) dimulai tahun 2010, telah didaftarkan sejumlah alutsista kondisi kritis, yang artinya wajib diganti segera.
Dampak lanjutannya adalah dukungan anggaran akan melemah atau tidak diprioritaskan, termasuk pengadaan dari pembiayaan luar negeri. Dengan merujuk indeks kekuatan militer GFP, kekuatan pertahanan Indonesia justru dinilai meningkat, bahkan belum membeli pesawat tempur dan kapal perang yang baru dan canggih sekalipun.
Asumsi postur pertahanan kita makin bagus karena merujuk GFP juga sedikit banyak mempengaruhi rendahnya dukungan terhadap inisiatif Kementerian Pertahanan akan Rancangan Peraturan Presiden untuk pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan sebesar Rp 1.750 triliun. Selain itu, tidak terlihat ada kebijakan pendanaan darurat untuk pengadaan alutsista saat kapal perusak (destroyer) China terlihat pertama kali di Laut Natuna Utara pada 13 September 2021.
Problem pelik lain adalah keterbatasan kemampuan APBN dalam pengadaan alutsista. Meskipun total anggaran pertahanan terlihat besar, seperti APBN 2021 sebesar Rp 120 triliun dan APBN 2022 sebesar Rp 134 triliun, tapi anggaran pengadaan alutsista yang tergolong belanja modal tidak lebih dari 20 persennya.
Upaya mendongkrak belanja modal dengan menambah penerimaan negara sangat sulit. Sejak 2018 rasio pajak (tax ratio) menurun menjadi kurang dari 10 persen. Bahkan, pada pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada DPR, 31 Mei 2021, rasio pajak ditargetkan 8,18 persen tahun 2021, dan menjadi 8,37 hingga 8,42 persen tahun 2022.
Sebagai perbandingan saat Indonesia membeli pesawat tempur baru Sukhoi 27/30 buatan Rusia tahun 2003, 2008, dan 2012, serta alutsista buatan AS berupa pesawat tempur F-16 tahun 2012 dan helikopter serang Apache tahun 2014, rasio pajak pada tahun-tahun pembelian alutsista tersebut berkisar Antara 10,9 hingga 12 persen.
Sumber utang luar negeri juga tidak mudah, utamanya setelah Covid-19 melanda dan perekonomian belum berjalan seperti sebelum pandemi global. Negara sebesar AS dan China malah sedang menghadapi krisis utang pemerintah dan swasta di dalam negerinya. Peluang berutang lebih besar untuk membeli alutsista takkan terbuka dalam waktu dekat.
Selain itu, karena Indonesia sudah mendorong bank sentral untuk berbagi beban dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN), maka negara dan kreditur asing juga memahami kemampuan bayar Indonesia melemah. Untuk tahun anggaran 2021 dan 2022 Bank Indonesia membeli SBN masing-masing Rp 215 triliun dan Rp 224 triliun.
Dengan beragam masalah di atas, pemerintah dan TNI perlu mempertimbangkan partisipasi rakyat dalam pengadaan alutsista. Jendela peluang itu sempat terlihat setelah tenggelamnya kapal selam Nanggala-402 pada 21 April 2021. Saat itu ada gerakan penggalangan dana oleh pengurus Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Detikcom (1/5) mewartakan dalam tiga hari (26-29 April) terkumpul uang Rp 1 miliar. Meskipun jumlah dananya jauh dari cukup untuk membeli sebuah kapal selam, namun inisiatif rakyat dan semangat bela negara perlu dibangkitkan.
Dasar hukum hibah dalam negeri bagi pengadaan alutsista adalah UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 38 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Pada Pasal 50 PP Nomor 10/2011 tertera sumber hibah dari dalam negeri antara lain, lembaga keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, lembaga lainnya dan perorangan.
Hibah dapat berbentuk uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan surat berharga (Pasal 42). Ketentuan serupa juga tercantum pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI Pasal 4 hingga Pasal 10. Namun, penerimaan hibah di lingkungan Kemhan dan TNI harus memenuhi pertimbangan teknis, ekonomis, politis dan strategis (Pasal 12 hingga Pasal 16).
Peluang pengadaan alutsista dengan pembiayaan hibah dalam negeri atau dari rakyat Indonesia sendiri perlu dioptimalisasi karena di satu sisi semangat bela negara rakyat sangat tinggi, dan di sisi lain kepercayaan publik kepada TNI juga demikian. Survei terakhir lembaga Indikator pada 17-21 September 2021 yang diberitakan detikcom (26/9) menunjukkan TNI adalah lembaga paling dipercaya --90 persen responden sangat atau cukup percaya.
Dua modal sosial (semangat bela negara rakyat dan kepercayaan publik kepada TNI) perlu dioptimalisasi pengambil kebijakan untuk mempercepat pengadaan alutsista TNI, utamanya penggantian alutsista kondisi kritis dan modernisasi alutsista tua.
Fahmi Alfansi P Pane alumnus Magister Manajemen Pertahanan, program kolaborasi Universitas Pertahanan Indonesia dan Cranfield University, Inggris; Tenaga Ahli DPR