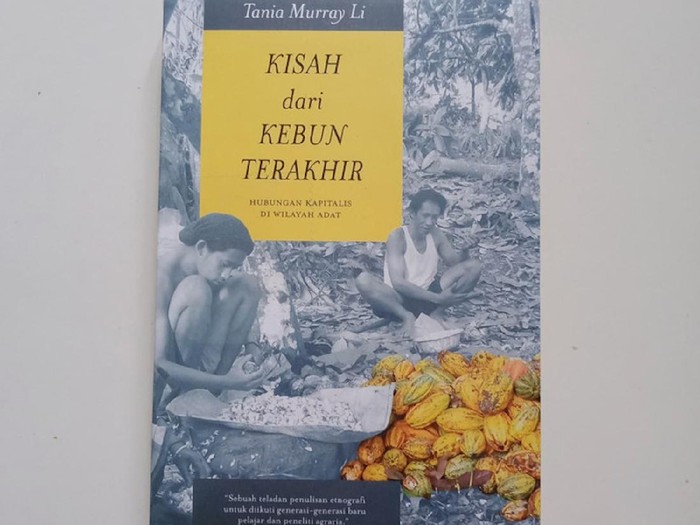Judul Buku: Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat; Penulis: Tania Murray Li; Penerjemah: Nadya Karimasari dan Ronny Agustinus; Penerbit: Marjin Kiri, Agustus 2020; Tebal: i – xiv + 326 halaman
Sebagai orang yang berasal dari pedalaman, membaca Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat membuat saya paham kenapa lahan mulai habis dan kesenjangan mulai terjadi di pedalaman. Perubahan ini tentu saja mengherankan, sebab masyarakat pedalaman begitu identik dengan rasa kebersamaannya yang tinggi.
Jiwa kolektivitas masyarakat pedalaman seharusnya tidak melahirkan kesenjangan. Kepemilikan lahan seharusnya bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Lalu, kenapa kondisi ini tidak bisa dipertahankan? Penelitian Tania Murray Li terhadap masyarakat Lauje, Sulawesi Tengah ini barangkali akan menjadi jawaban alternatif untuk memahami perubahan yang sering kali terjadi di wilayah pedalaman.
Dalam penelitiannya, Tania berfokus pada masyarakat Lauje, baik itu yang tinggal di pesisir maupun perbukitan. Penelitian etnografis yang dilakukan selama dua puluh tahun (1990-2009) tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Lauje di perbukitan tidak selalu menolak narasi pembangunan dan modernisasi. Mereka malah ingin merasakan derap langkah kemajuan dan pembangunan. Tanpa disadari, hasrat ini lalu menyeret mereka untuk bersaing satu sama lain dalam praktik kapitalisme yang kemudian berujung pada kesenjangan. Namun, perlu diketahui bahwa hasrat masyarakat pedalaman untuk merasakan modernisasi tidak muncul begitu saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Stereotip yang dilekatkan kepada masyarakat perbukitan oleh warga pesisir dinilai telah menjadi pemicu atas munculnya hasrat tersebut. Warga pesisir memandang penghuni perbukitan sebagai orang yang terbelakang. Mereka dianggap norak, jorok, dan bodoh karena tidak pandai berhitung dan berbahasa Indonesia. Tania menilai bahwa upaya merendahkan ini adalah "salah satu cara orang pesisir Lauje untuk menegaskan jarak di antara mereka dan meneguhkan keunggulan diri."
Pandangan ini ternyata meresap ke dalam diri orang-orang perbukitan. Mereka kemudian menilai bahwa kondisi hidup mereka memang jauh berbeda dengan warga pesisir. Oleh karenanya, mereka berjuang untuk menggapai kesejahteraan yang sama. Hasrat ini pulalah yang kemudian membawa orang Lauje di perbukitan turun ke pesisir untuk melakukan hubungan jual-beli dengan para pedagang.
Para pedagang tidak hanya mendapat keuntungan dari hasil hutan yang dibawa oleh masyarakat perbukitan, tapi juga memanfaatkan tenaga kerja mereka. Awalnya warga perbukitan tidak sepenuhnya bergantung kepada para pedagang. Mereka hanya menjual hasil hutan dan bekerja pada saat tertentu saja. Namun, permainan licik pedagang dalam hal upah kerja membuat masyarakat perbukitan jatuh dalam jebakan utang.
Selain itu, hasrat untuk terus mengonsumsi barang-barang pasar juga menyeret mereka dalam jebakan yang sama, yaitu utang. Jebakan utang dan hasrat konsumsi ini disebut oleh Tania sebagai "paksaan" dan "keterpikatan". Tania menjelaskan bahwa keduanya, "berpadu membentuk hubungan ekstraktif antara pedagang pesisir dan penghuni perbukitan yang merupakan sumber keuntungan bagi pedagang."
Selain itu, faktor gagal panen akibat kekeringan juga membuat masyarakat perbukitan hidup dalam kondisi kerawanan. Mereka lalu memilih untuk menanam kakao, jenis tanaman yang dinilai lebih aman dan menguntungkan dibanding tembakau dan bawang merah. Akibat yang kemudian tidak mereka duga dari tanaman jangka panjang ini ialah pengavelingan lahan bersama. Hubungan antarsesama yang sebelumnya berjalan baik mulai mengalami goncangan.
Lahan yang awalnya digarap dengan cara kerja sama perlahan bergeser menjadi arena persaingan. Seperti halnya hubungan antara masyarakat perbukitan dan pedagang pesisir yang dijalankan dengan paksaan dan keterikatan, pergesekan antarsesama warga perbukitan juga diwarnai oleh hal serupa: paksaan atau ancaman dari orang-orang yang punya kuasa di pedalaman, dan hasrat masyarakat pedalaman itu sendiri untuk hidup sejahtera.
Petani yang gagal ini kemudian berutang kepada para rentenir petani perbukitan dan pedagang pesisir dengan menyerahkan lahan mereka sebagai jaminan. Mirisnya, utang tersebut sering kali tidak mampu terbayar oleh para petani kecil, sehingga akumulasi lahan oleh para petani yang lebih beruntung dan pedagang pesisir pun terjadi.
Lahan bukan satu-satunya hal yang diserahkan oleh para petani kecil di perbukitan. Sejak ketimpangan ini terjadi dan lahan sudah tidak lagi dimiliki, mereka lalu mengorbankan tenaga kerja mereka untuk disedot oleh para kapitalis perbukitan dan pedagang pesisir. Hubungan ini tentu saja membabat habis otonomi diri yang mereka miliki di masa lalu. Dulu, mereka hanya bekerja saat mereka mau saja. Pasca kehabisan lahan, mereka terpaksa dan harus bekerja demi mencukupi kebutuhan, meskipun dengan upah yang menurut mereka tidak sesuai.
Menariknya, ketimpangan yang telah terjadi tidak menimbulkan perlawanan atau evaluasi ekonomi moral dari kalangan petani kelas bawah. Tania melihat bahwa mental ini kemungkinan besar disebabkan oleh prinsip warga perbukitan Lauje yang sudah terbentuk sejak lama, yaitu keyakinan mereka terhadap kerja keras dan tanggung jawab pribadi sebagai faktor penentu kesuksesan.
Oleh karenanya, mereka melihat ketimpangan ini sebagai hasil dari kegagalan diri, bukan dampak dari sistem perekonomian yang telah mereka praktikkan. Kalaupun ada protes yang mereka suarakan, fokus mereka bukan pada "kemiskinan, utang, atau lepasnya lahan, melainkan kegagalan pemerintah untuk memenuhi janji-janji pembangunan," jelas Tania.
Mereka tidak menduga bahwa pembangunan yang mereka harapkan kelaknya malah mempertajam ketimpangan di antara mereka. Misalnya, akibat pembangunan jalan, pedagang pesisir akhirnya dapat dengan mudah mengakses dan menguasai lahan yang ada di perbukitan.
Sikap orang Lauje perbukitan di atas tidak hanya membingungkan Tania sebagai peneliti. Para aktivis gerakan sosial yang selama ini kukuh untuk mempertahankan keberadaan masyarakat adat beserta lahan mereka juga kebingungan, dan akhirnya tidak tau apakah harus membantu mereka atau tidak.
Masyarakat Lauje perbukitan tidak menolak pembangunan. Mereka tidak dijerat oleh perusahaan besar. Hilangnya lahan bukan karena dirampas, melainkan karena utang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan modal pertanian. Sulitnya lagi, tidak ada perjuangan kolektif yang mereka bangun untuk menghentikan sistem yang telah menjerat mereka. Dari kisah perjalanan kemiskinan yang nyata ini, pembaca kemudian akan memahami bahwa telah terjadi dampak yang tidak diantisipasi oleh teori pembangunan.
Bagi para perencana pembangunan, persaingan adalah hal yang mutlak untuk mencapai produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kasus masyarakat perbukitan Lauje, persaingan sengaja dibiarkan agar lahan yang dulunya tidak dianggap kini jadi lebih menghasilkan setelah adanya pertanian. Petani yang kalah dalam persaingan diminta untuk keluar dari arena dan mencari pekerjaan baru.
Namun, sedikitnya lapangan pekerjaan di Indonesia tidak mampu menyerap para masyarakat Lauje perbukitan yang telah gagal dalam usaha pertanian, sehingga membuat mereka semakin terlunta-lunta. Oleh karena itu, Tania dengan bijak mengatakan bahwa, "Pertumbuhan bisa berguna, tetapi kebijakan mendorong pertumbuhan perlu mengantisipasi kemiskinan yang tercipta --secara rutin dan terprediksi-- bersama pertumbuhan itu."
Setelah membaca buku ini, saya kemudian mulai bisa memahami kenapa telah terjadi pergeseran sosial dan ekonomi di wilayah pedalaman. Membaca hasil penelitian Tania ini benar-benar membuat saya merasa tercerahkan. Selain metode etnografi dan panjangnya waktu penelitian, analisis konjungtur yang digunakan oleh Tania membuat penelitian ini begitu kaya. Pemilihan analisis ini bagi Tania, "memungkinkan ia menggali bagaimana unsur-unsur yang berbeda saling berpadu."
Dalam hal ini, ia mengeksplorasi berbagai elemen yang ada di lapangan, mulai dari elemen ekonomi, material lingkungan, jenis dan kondisi tumbuhan, aturan dan nilai-nilai sosial, hasrat dan pemaknaan, hingga keberadaan arwah yang diyakini masyarakat Lauje. Metode dan pendekatan ini menyediakan perjalanan kilas-balik sejarah yang memukau.
Ia berupaya melihat kejadian dalam tempat dan waktu tertentu, lalu mencermati apa akibat dan kemungkinan dari kejadian tersebut di masa depan, juga kejadian apa yang sebelumnya ada di belakang. Mula-mula, ia menyoroti nasib menyedihkan dari petani perbukitan Lauje yang digambarkan di bagian pendahuluan. Setelah itu, bab demi bab berikutnya, ia mundur jauh ke belakang untuk memberikan gambaran terkait situasi dan kondisi yang telah terjadi.
Dengan begitu, secara perlahan pembaca akan memahami proses dari perubahan dan pergeseran pada masyarakat Lauje di perbukitan. Dari penelitian ini kita akhirnya tahu bahwa pembangunan memang sulit dielakkan. Bagi sebagian orang, terutama di pedalaman, pembangunan mungkin telah menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, kita tidak bisa sepenuhnya menolak pembangunan, tapi kita bisa bersikap kritis terhadapnya, apakah dalam perjalanannya pembangunan ini mampu memberikan kesejahteraan untuk semua, atau tidak?