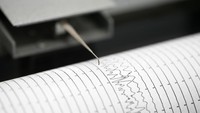Pada 13 Februari 1633, Galileo Galilei diadili. Ia yang mendukung teori Helocentris Copernicus, dianggap menentang keyakinan Gereja Katolik yang waktu itu mempercayai bumi sebagai pusat alam semesta, teori Geocentris. Pendapat yang meresahkan masyarakat, menurut pemuka gereja.
Akhirnya, pada April 1633, Galileo bersedia mengaku bersalah untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Ia dijatuhi hukuman penjara dan menjalani status tahanan rumah seumur hidup. Teorinya juga dilarang.
Hampir 3 abad kemudian, pada 31 Oktober 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan penyesalan terkait tindakan yang dilakukan Gereja Katolik terhadap Galileo. Paus Yohanes Paulus II mengumumkan bahwa Gereja Katolik telah melakukan kesalahan saat menghakimi pandangan keilmuan Galileo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saya sudah sering membaca cerita tentang abad kegelapan ini. Tapi kali ini saya bertanya-tanya, apakah Gereja Katolik tetap merasa bersalah telah menghukum Galileo andai teori Helocentris Copernicus terbukti salah secara sains?
Jika pertanyaan ini dilontarkan kepada pegiat kebebasan berpendapat, jawabannya pasti. Gereja Katolik bersalah karena merampas kebebasan manusia berpendapat. Tak peduli benar atau salah.
Ya, kebebasan berpendapat ini yang kemudian menjadi kredo baru sejak abad pencerahan hingga hari ini. Manusia harus dibebaskan sebebas-bebasnya untuk berpendapat. Demokrasi mengadopsinya.
Kemudian muncul kepercayaan baru dengan istilah "kebebasan yang bertanggung jawab". Kebebasan yang dibatasi hak orang lain. Bentuknya di Indonesia antara lain adalah UU ITE. Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dinyatakan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" diancam hukuman pidana.
Pasal inilah yang digunakan polisi untuk menjerat drummer grup band Superman is Dead, Jerink, atas pengaduan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali. Drummer itu menulis di akun Instagram-nya: "Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah Sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19."
Direktur Reskrimsus Polda Bali Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho menganggap unggahan itu memiliki unsur penghinaan dan menimbulkan permusuhan.
Penangkapan atas Jerinx segera diikuti kontroversi pendapat umum. Satu pihak mendukung, yang lain menolak.
Pihak yang setuju penerapan UU ITE beralasan bahwa informasi yang tidak benar, hoax, akan menimbulkan keresahan, menyesatkan masyarakat, dan merugikan nama baik suatu lembaga atau perorangan.
Misi luhurnya jelas. Argumen yang jadi konsideran adalah melindungi masyarakat dari informasi yang meresahkan, dan melindungi nama baik orang.
***
Mungkinkah masyarakat bisa dilindungi dari informasi yang meresahkan? Bisakah informasi dikontrol oleh undang-undang agar tak ada orang atau lembaga yang merasa tercemar nama baiknya?
Ini era baru dengan teknologi yang membuat masyarakat dibanjiri dan membanjiri informasi selama 24 jam. Banjir informasi yang mustahil membuat orang bisa tenang, tidak resah, tiap kali pemerintah dan masyarakat melaporkan korban baru Corona. Dan, angka penambahan kasus baru yang kurvanya terus menanjak naik jelas bukan hal yang tidak meresahkan masyarakat.
Masih banyak informasi lain, mulai dari jutaan angka PHK, tanda-tanda pasti Indonesia akan memasuki resesi, kasus kletih di Jogja. Mungkinkah masyarakat dibebaskan dari informasi yang meresahkan? Jelas tidak.
Bagaimana dengan cita-cita melindungi lembaga atau perorangan dari informasi yang menghina dan mencemarkan nama baik?
KUHP Pasal 310 ayat (1) berbunyi: Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Jelas yang jadi objek penghinaan adalah personal, seseorang. Bukan lembaga macam IDI, paguyuban penggemar perkutut, atau lembaga formal dan non formal lain. Demikian KUHP menegaskan.
Oleh karena itu, jika pasal penghinaan yang jadi acuan UU ITE pasal 27 ayat 3 adalah pasal penghinaan dalam KUHP, IDI dan lembaga lain bukan pihak yang dimaksudkan oleh pasal 310 KUHP, pihak yang diserang kehormatannya. IDI adalah lembaga bukan perorangan.
Apakah KUHP alpa mencantumkan lembaga sebagai pihak yang mestinya mendapatkan perlindungan dari pencemaran nama baik/penghinaan?
Saya menduga KUHP memandang lembaga secara berbeda. Terhina adalah urusan rasa. Rasa yang hanya dimiliki secara perorangan. Lembaga bisa berganti orang dari waktu ke waktu dan tidak bisa dibayangkan memiliki rasa.
Lebih dari itu, lembaga memiliki kebijakan, tindakan yang berimplikasi sangat luas bagi kebaikan dan kerugian orang banyak. Karena itu wajar ia dikontrol, yang salah satunya adalah pendapat orang atas dirinya. Ini bisa berupa kritik pedas yang dimaknai penghinaan.
Pendapat Jerinx atas IDI didasari atas penilaian dia dengan argumen yang entah sesat, bengkok, atau tak berdasar. Saya melihat Jerinx ngawur dan bodoh dalam berkesimpulan. Bagaimana andai pendapat dia atau orang lain atas IDI benar tapi IDI merasa terhina?
Jika setiap pendapat yang menimbulkan rasa terhina harus dibungkam, padahal pendapat itu bermanfaat untuk kebaikan dan perbaikan apa juga harus dilarang? Misalnya, apa kesimpulan persepsi korupsi yang menempatkan kepolisian dan kehakiman serta DPR sebagai lembaga terkorup juga dilarang, karena lembaga polisi dan kehakiman terhina?
Ini tidak berarti saya menginginkan tidak ada pembelaan bagi lembaga yang dicela atau dihina. Ada bentuk pembelaan yang lebih low cost yang tidak menghilangkan peluang kebenaran muncul dari sebuah kritik. Seperti kebenaran teori Helocentris yang dikubur sekian abad karena menimbulkan keresahan.
IDI atau lembaga lain bisa membantah suatu penilaian yang menghina. Kemukakan data dan argumennya. Atau tantang Jerinx berdebat secara terbuka. Publik akan menilai apakah IDI kacung WHO atau Jerinx yang bego. Sederhana itu.
Tiap kali UU ITE ditetapkan, saya ingat Orde Baru (Orba). Beberapa puluh tahun lalu, lewat TV hitam putih di rumah Pak Lurah, saya menonton Jenderal Benny Moerdani menjelaskan kepada pers Kasus Tanjung Priok yang baru saja terjadi. Jenderal Benny berbisik-bisik kepada Pangdam Jaya Jenderal Try Soetrisno waktu ditanya berapa korban meninggal. Tiga puluh sambilan, jawab dia mantap. Lama kemudian saya tahu, jumlah korbannya ratusan.
Sama dengan semangat UU ITE, Jenderal Benny bermaksud "baik", menjaga agar masyarakat tidak resah dan takut karena sebuah informasi. Demikian juga dengan kebijakan pemerintah Orba yang lainnya. Informasi dikontrol sedemikian ketat, aparat menelpon redaksi jika ada kasus yang sensitif. Mana yang boleh dan tidak boleh ditulis media. Tujuannya adalah melindungi masyarakat agar tidak resah.
Jika UU ITE memiliki cita-cita luhur seperti Orba, ya siapkan infrastruktur represi yang lebih masif. Kontrol semua pejabat, lembaga, dan pemilik gadget agar tercipta masyarakat adem ayem, yang damai tenteram, bebas dari informasi meresahkan. Meski adem ayem, yang suatu saat bisa meledak menjadi keguncangan.