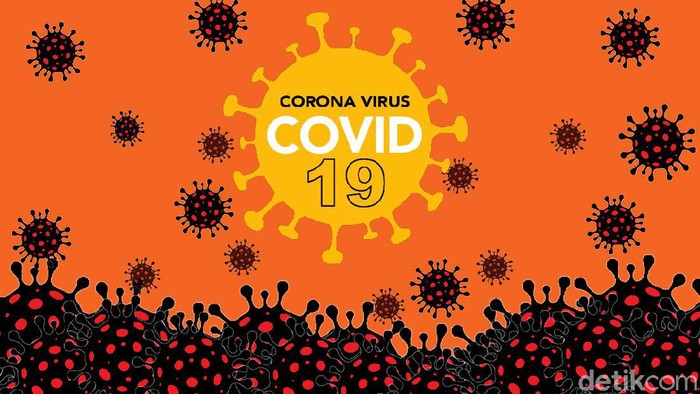"Peran pemerintah adalah membujuk (masyarakat) untuk menyalahkan diri sendiri," tulis ilmuwan politik Amerika Serikat Lawrence Mead dalam risalah pentingnya Beyond Entitlement (1986). Mead secara personal merupakan pendukung utama tesis culture of poverty atau "budaya kemiskinan", sebuah keyakinan bahwa orang miskin hanya menyalahkan diri sendiri atas kemiskinan mereka.
Namun, kredonya soal "membujuk masyarakat untuk menyalahkan diri sendiri" menjadi cermin yang pas hari ini, terutama melihat strategi pemerintah Indonesia dalam menangani krisis pandemi akibat virus corona. Sebagaimana ditulis Kenan Malik dalam kolomnya di The Guardian bahwa tema utama pandemi adalah "pengakuan atas dampaknya yang tidak setara: orang miskin, lansia, dan minoritas terdampak lebih parah."
Di sisi lain, para pemangku kebijakan berusaha menjauhkan diri mereka dari konsekuensi kebijakan yang telah mereka ambil: kasus positif yang melonjak drastis, pengujian yang tak merata, kurangnya alat pelindung diri, banyaknya tenaga medis yang gugur, hingga ancaman krisis ekonomi. Di samping, mereka coba mencari kambing hitam atas situasi tersebut: masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mari flashback! Ketika negara lain telah tumbang akibat infeksi virus corona tipe baru, sebut saja Tiongkok serta jiran Malaysia dan Singapura, pemerintah Indonesia malah dengan semangat mengucurkan dana secara jor-joran untuk influencer demi promosi pariwisata. Beberapa menteri juga berasumsi bahwa wabah ini ringan. Dalam bahasa mereka, "negara kita dijamin aman!", "kita kebal virus karena makan nasi kucing", beserta bahasa-bahasa aneh dan menyepelekan lainnya.
Kemudian, ketika kasus pertama ditemukan, serangan panik melanda masyarakat secara meluas. Alhasil, peran utama pemerintah --seperti ditulis Mead-- pun muncul. Pemerintah, melalui Menkes Terawan, menyerang sikap masyarakat yang ia anggap egois, dan menyebabkan persediaan masker menjadi langka, alih-alih merefleksikan sikap awal mereka. Sialnya, kondisi ini tak hanya terjadi di Indonesia.
Sejarah Panjang
Menyalahkan orang miskin dan minoritas atas ketidakberhasilan suatu pemerintahan punya sejarah panjang, bahkan sama tuanya dengan peradaban kita. Sejak gagasan Victoria di Inggirs tentang "underserving poor", culture of poverty pada 1960-an, hingga "mengutuk" orang-orang miskin akibat krisis pandemi hari ini, menunjukkan bahwa di jantung sejarah kita, kemiskinan dilihat sebatas masalah moral ketimbang politik, serta masalah individu alih-alih masyarakat.
Pada 2012 lalu, editorial The Guardian mengkritisi sikap Uskup Agung Carterbury, Inggris yang menghardik orang-orang miskin dan mengatakan bahwa "mereka tak layak mendapatkan tunjangan". Karena menurutnya dengan meletakkan dirinya sebagai contoh keberhasilan, orang-orang harus bekerja keras untuk mencapai posisi di atas. Namun, ada yang luput dari pandangannya: kemiskinan struktural.
Adanya kemiskinan struktural, maka menimbulkan pula yang dinamakan "budaya-menyalahkan-orang-miskin struktural". Hal ini terlihat dengan berbagai sikap menyalahkan orang miskin atas kondisinya, melabeli bahwa yang miskin dekat dengan tindakan kriminalitas, hingga mengklaim orang miskin memiliki sikap tertib aturan yang rendah. Label terakhir, hari ini, dijadikan pemerintah Indonesia sebagai alibi untuk menjawab mengapa persebaran kasus begitu besar.
Masyarakat, khususnya yang miskin, sekali lagi, dijadikan kambing hitam. Dalih pemerintah, mereka yang "masih berkerumun", "tak mau memakai masker", "masih bepergian", "masih keluar rumah" sebagai pelaku tunggal penyebar virus. Namun, mereka lupa bahwa apa yang dihadapi masyarakat bukan perkara moral, tapi masalah politik.
Alih-alih menyusun kebijakan strategis dengan pendekatan yang politis, pemerintah justru lebih senang mengklaim keberhasilan-keberhasilan kecil mereka dan melupakan kesalahan besar --yang sejatinya itulah muara malapetaka. Data dan statistik telah membuktikan. Jika kita menganalisis bank data angka corona di Worldometers atau Johns Hopkins University, negara dengan kematian terbanyak bukanlah yang paling miskin, terpadat, terbelakang, atau terkaya sekalipun, melainkan yang dipimpin oleh rezim populis.
Di tiga besar, misalnya, ada Trump bagi AS, Modi di India, dan Bolsonaro di Brasil. Sementara di luar itu, menyusul nama-nama seperti Obrador, Duterte, Boris Johnson, hingga Jokowi (kalau mau dikatakan populis), keteteran menghadapi virus. Narasi mereka sama; kebanyakan menolak rekomendasi pakar, merasa telah berupaya dengan gigih, dan pastinya menyalahkan masyarakat sebagai "individu yang tak patuh".
Berandai-Andai
"Dalam beberapa minggu terakhir, angka kasus positif rata-rata seribu per hari. Bahkan bisa lebih dari dua ribu kasus. Inilah pentingnya kita semua mengingatkan kalau kita tidak cukup disiplin sendiri. Tanggung jawab kita ajak yang lain disiplin," kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai Rapat Terbatas, Senin (27/7). Apa yang kita dapat dari pernyataan tersebut?
Setelah serangkaian drama "penyepelean" virus oleh Terawan dan kolega, ujaran tendensius Ahmad Yurianto terkait "si kaya dan si miskin" (yang memperlihatkan betapa diskriminatifnya pemerintahan kita), hingga ucapan Doni setelah Indonesia "pecah telur" di 100 ribu kasus, sekali lagi kita mengamini tesis Lawrence Mead.
Padahal, ketimbang mencari kambing hitam, pemerintah harus berefleksi karena setidaknya ada empat kebijakan pemicu interaksi yang patut dikritisi, mulai dari pembukaan mal, pariwisata, pengembalian aktivitas bekerja di kantor-kantor, hingga pengoperasian transportasi umum.
Tentu banyak pertimbangan di baliknya, baik ekonomi, sosial, ataupun politik. Namun, ada satu akar yang menyebabkan segala masalah makin buram dalam penanganan Covid-19 di Indonesia: pengambilan kebijakan yang tidak didasari landasan ilmiah. Implikasinya sederhana. Kajian ilmiah dapat jadi panduan bagi pemerintah menetapkan turunan-turunan kebijakan, termasuk berbagai protokol yang lebih tepat dan terukur. Namun, tak dilakukan.
Celakanya, nasi telah menjadi bubur, dan virus corona kadung merebak bahkan hampir sepenjuru negeri; tak ada yang bisa sembunyi! Kebijakan politik amburadul pemerintah justru dibalas dengan pernyataan moralis kepada masyarakat, yang tentu, sulit bagi kita untuk balik membalasnya.
Kita hanya bisa berandai-andai, bagaimana jika dulu, pada Februari lalu, pemerintah bertindak sigap atau Terawan tidak meremehkan virus ini? Tentu kita hanya bisa berandai-andai. Karena sebagaimana kata Mead baru-baru ini, kita layaknya Hispanik di Amerika sana. Hakiki kita sebagai warga negara adalah "berandai-andai" dan "disalahkan".