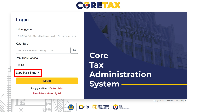Penerbitan uang baru ini seakan menjadi kelanjutan dari tren periodik sebelumnya. BI selalu menerbitkan uang rupiah khusus sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 1970, misalnya, BI menerbitkan sembilan uang koin dengan ragam nominal antara Rp 200 sampai Rp 25.000.
Kemudian pada 1995, BI juga mengeluarkan dua uang rupiah khusus yakni uang koin masing-masing bernominal Rp 300.000 dan Rp 850.000. Dua uang yang di dalamnya menyematkan gambar Presiden ke-2 RI Soeharto ini dikenal sebagai uang Seri 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Penerbitan uang baru semacam ini menurut rencana akan dilakukan setiap 25 tahun sekali sebagai ungkapan rasa syukur. Kendati merupakan jenis uang peringatan (commemorative money) yang diterbitkan secara khusus, rilis uang rupiah pecahan baru seperti ini agaknya tidak lepas dari sejumlah persoalan yang sangat fundamental.
Penerbitan uang baru Rp 75.000 menjadi sejarah pertama kali bernominasi lebih rendah daripada uang beredar yang masih berlaku. Merujuk kembali pada tiga kasus di atas, uang khusus antara Rp 200 sampai Rp 25.000 ketika itu belum ada. Demikian pula, uang koin bernominal Rp 300.000 dan Rp 850.000 pada dasawarsa 1990-an belum eksis.
Persoalan akan sedikit berbeda seandainya nominal uang khusus tersebut relatif besar, misalkan Rp 750.000 atau Rp 7,5 juta, untuk tetap mempertahankan angka 75. Perasaan bangga niscaya akan hinggap di hati para pemegangnya lantaran besaran nominal yang tidak lazim (setidaknya untuk saat ini), unik, momental, dan langka.
Jika melihat semata-mata pada besaran nominalnya, uang pecahan baru Rp 75.000 agaknya lebih cocok diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi alih-alih sebagai uang peringatan. Pecahan uang nominal Rp 75.000 bisa untuk mengisi kekosongan di antara dua pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000.
Jarak antara kedua uang pecahan terbesar itu sangat boleh jadi terpaut terlalu jauh. Dengan demikian, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan akan uang tunai disesuaikan dengan nilai transaksinya. Kepraktisan dalam melakukan transaksi adalah manfaat lain yang bisa diturunkan dari rilis uang pecahan baru semacam ini.
Penerbitan uang baru secara khusus alih-alih secara reguler juga layak dikedepankan. Pengedaran uang kertas rupiah pecahan baru Rp 75.000 diklaim bukan pencetakan uang baru yang ditujukan secara bebas dan tersedia di masyarakat dan bukan tambahan likuiditas kebutuhan pembiayaan atau pelaksanaan kegiatan ekonomi.
Klaim tersebut sejatinya bisa dipenuhi dari penerbitan uang baru secara reguler. Untuk memperoleh uang baru, masyarakat toh harus menukar uang rupiah lama dengan nilai yang ekuivalen. Alhasil, penggantian uang lama dengan uang baru pun terjadi. Uang yang baru ini bisa digunakan untuk belanja sebagai alat tukar yang sah.
Dalam skala yang lebih luas, emisi uang baru ini agaknya juga kontradiktif dengan wacana redenominasi yang digulirkan Kementerian Keuangan. Ide redenominasi muncul kembali ke permukaan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.
Apabila redenominasi benar-benar dilakukan pada 2024, usia 'hidup' uang baru pecahan Rp 75.000 ini hanya bertahan selama kurang dari empat tahun. Padahal ongkos cetak uang rupiah --mulai perencanaan hingga distribusinya ke seluruh Nusantara, bahkan sampai pemusnahan jika sudah tidak layak edar-- sangatlah mahal.
Cerita kontradiktif sepertinya juga berlaku bagi BI. Pada 1 Januari 2018, BI menginisiasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Sistem GPN berfungsi sebagai sentral penghubung antar-switching pada sistem pembayaran sehingga dapat menghemat biaya operasional transaksi antarbank yang dibebankan kepada nasabah.
Segaris dengan itu, pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan persis setahun lalu, BI juga mencanangkan QRIS (Quick Response Indonesia Standard) yang berlaku efektif per 1 Januari 2020. Metode pembayaran non tunai ini berlaku untuk semua aplikasi pembayaran uang elektronik server based, dompet elektronik, dan mobile banking.
Di satu sisi, penerbitan uang baru terkesan memberikan perhatian ekstra bagi uang konvesional. Di sisi lain, inisiasi pengembangan sistem GPN dan QRIS yang berbasis pada teknologi digital mendorong metode pembayaran transaksi non tunai dalam rangka mewujudkan cashless society.
Alhasil, terbitnya uang peringatan mendorong masyarakat cenderung untuk menyimpannya berlama-lama. Jika ini yang terjadi, uang akan kehilangan fungsi sebagai alat tukar. Uang peringatan berubah fungsi menjadi barang 'koleksi'. Konsekuensinya, perputaran uang yang mengikuti transaksi barang/jasa juga tertekan.
Dengan pecahan nominal Rp 75.000, dicetak terbatas 'hanya' 75 juta lembar, dan tidak beredar bebas, pengendapan tenaga beli mencapai Rp 5,625 triliun. Ironisnya, pengendapan tenaga beli terjadi di kala belanja konsumsi rumah tangga diunggulkan sebagai penangkal gejala resesi.
Sampai di sini, penerbitan uang anyar senantiasa akan dimaknai berbeda-beda atas dasar pemahaman sendiri-sendiri. Perbedaan pemahaman kian runcing terkait dengan kepentingannya masing-masing. Jika demikian, persepsi publik yang terbentuk sangat boleh jadi berbenturan dengan sasaran utama dari penerbitan uang.
Uang harus dimerdekakan sesuai jati dirinya alih-alih dijajah dengan atribut uang peringatan kemerdekaan. Manfaat ekonomi yang didapat dari uang peringatan secara objektif tidak sebanding dengan ongkos finansial yang dibayarkan. BI dan Kementerian Keuangan bisa mencari alternatif bentuk lain sebagai ekspresi rasa syukur.
Merdeka!
Haryo Kuncoro Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta
(mmu/mmu)