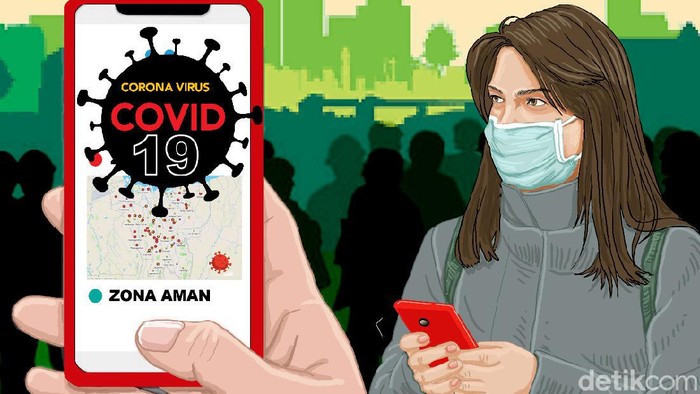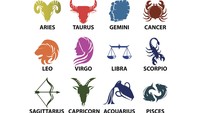Virus corona baru (Covid-19) telah menimbulkan kebingungan besar di berbagai kalangan dengan tingkat pengetahuan, latar belakang sosial, dan kultural yang berbeda. Setiap kelompok memberi respons berdasarkan model penalaran dan kepentingannya sendiri, di samping pengalaman sebelumnya dalam menangani penyakit menular.
Hal tersebut di satu sisi telah melahirkan pengetahuan yang kaya dan beragam, namun di sisi lain sekaligus juga dapat menambah kebingungan yang telah melanda sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa virus corona bukan semata entitas alami yang berdiri sendiri, melainkan telah menjadi entitas kultural dan politik yang melibatkan sistem nilai, praktik dan kebiasaan, sentimen dan emosi, serta kepentingan dan kekuasaan.
Dalam kaitannya dengan keseluruhan hal tersebut, kita dapat melihat kemampuan virus ini sebagai agency yang mengubah sekaligus membentuk formasi sosial, pandangan politik dan religi, hingga hubungan manusia dengan alam. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai tingkat "kecerdasan" suatu masyarakat dalam menangani krisis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.
Dalam kasus Indonesia, menarik untuk melihat perbedaan respons antara masyarakat yang telah terbiasa dengan bencana seperti di Aceh, Jogja, dan Palu dengan daerah-daerah lain yang jarang atau belum pernah mengalami bencana. Di samping itu, respons masyarakat berdasarkan kelas sosial dan akses sumber daya juga tak kalah penting untuk diamati, terutama dalam usaha mereka mengatasi keterbatasan dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada.
Secara umum, proses yang terjadi belum tentu tepat, baik di tingkat individu, masyarakat, dan pemerintah. Dalam hal pemerintah, pertimbangan dilakukan bukan semata berdasarkan ilmu kesehatan, namun juga kapasitas ekonomi, keamanan nasional, serta kepentingan politik orang-orang di pemerintahan.
Di tingkat individu dan masyarakat akan berlangsung lebih rumit lagi, namun dengan dampak keputusan yang lebih kecil. Sebagai contoh, bagi masyarakat, para ahli kesehatan bukan tokoh acuan dalam kehidupan sehari-hari, berbeda misalnya dengan agamawan dan tetua adat. Penanganan virus, terutama dalam hal sosialisasi, akan memerlukan negosiasi antara pemerintah setempat, para ahli kesehatan, dan tokoh lokal yang dipercaya oleh masyarakat.
Proses negosiasi mereka telah menimbulkan dinamika dan pengetahuan yang beragam. Bagi para ilmuwan kesehatan, virus corona dipandang sebagai tantangan ilmiah yang melahirkan kontestasi dalam pembuatan model pendataan, penularan, dan penanganannya. Namun, kenyataan virus ini terus menular hingga mencapai jumlah penderita yang mencengangkan membuat tidak sedikit orang yang mempertanyakan otoritas ilmiah mereka.
Di masa normal, kepakaran diproduksi melalui jalan penjenjangan akademis atau kredensial, namun di masa krisis masyarakat lebih menuntut pada pembuktian kepakaran dalam bentuk penanganan krisis secara langsung. Dengan kata lain, virus corona telah memaknai kepakaran lebih luas dari ruang lingkup sains dan akademis, melainkan pada tanggung jawab sosial dalam kehidupan konkret.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Respons yang paling mengundang perdebatan terdapat di bidang keagamaan. Tidak sedikit kalangan agama yang memandang virus sebagai ujian bagi ketakwaan mereka, sehingga mereka memutuskan tetap melakukan ritual secara komunal yang justru menjadi wahana penularan wabah. Pertemuan Ijtima Ulama di Gowa, Sulawesi; pertemuan para pendeta di Lembang, Bandung; pertemuan umat Kristen di Korea Selatan, dan banyak lagi.
Bahkan kendati doktrin intrinsik agama telah melarang mereka melakukan ritual komunal (misalnya, dalam Islam terdapat hadis Nabi yang melarang orang bepergian di tengah wabah), mereka tetap tidak mengindahkannya.
Hal tersebut di satu sisi menunjukkan adanya keterbatasan mereka dalam memahami agamanya sehingga justru mengambil keputusan yang berlawanan dari doktrin. Di sisi lain, secara sosiologis ritual keagamaan merupakan mekanisme kultural yang biasa dilakukan untuk menghadapi ketegangan di tengah krisis (ritual of the passages), sehingga semakin besar dampak yang ditimbulkan oleh virus corona semakin besar pula dorongan untuk melakukan ibadah secara bersama-sama.
Dengan kata lain, mereka melakukan ritual komunal berdasarkan pengalaman yang ada, dengan tanpa menyeleksi secara lebih rinci terhadap jenis bencana dan doktrin agama yang dianggap relevan.
Di luar contoh-contoh tadi, terdapat contoh-contoh lain yang cukup sukses dalam negosiasi antara para agamawan, pemerintah, dan para ahli kesehatan. Paus Franciscus telah memutuskan melakukan misa Paskah secara virtual, tanpa pertemuan jamaah di Basilika Santo Petrus. Rektor Al-Azhar melakukan hal yang sama, termasuk melarang Salat Jumat di daerah yang rawan penularan.
Di Indonesia, Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj memberi imbauan agar masyarakat tetap tinggal di rumah sambil menunjukkan data dari para ahli kesehatan dan pemerintah. Hal yang kurang lebih sama juga dilakukan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah.
Di samping menunjukkan suksesnya negosiasi antara agamawan, ahli kesehatan, dan pemerintah, keputusan-keputusan tadi juga menunjukkan usaha rasionalisasi agama lewat sains serta usaha distribusi pengetahuan ilmiah melalui doktrin dan tokoh-tokoh agama, sehingga masyarakat akan memandang dan menerima pengetahuan sains layaknya ajaran agama yang tak semata dipandang sebagai pemikiran melainkan juga sebagai keyakinan.
Secara politis, proses tersebut telah mendorong budaya kepatuhan di kalangan masyarakat di mana penyelamatan warga dilakukan melalui mekanisme kontrol secara kultural dan meminimalisir pengerahan aparatus keamanan.
Implikasi dari negosiasi-negosiasi di atas, dengan proses yang berbeda-beda di berbagai kawasan, adalah terjadinya karantina terhadap miliaran manusia di seluruh dunia. Masyarakat dengan "suka rela" menerima anjuran untuk didomestifikasi dari ruang-ruang publik dan mengubah interaksi sosial secara langsung menjadi lebih berjarak dengan menggunakan wahana teknologi komunikasi. Ini merupakan rekayasa ruang, model sosialisasi, dan penerimaan kepatuhan terbesar dalam sejarah umat manusia.
Di masa lalu, praktik tersebut dilakukan melalui kekuatan politik totaliter; sekarang, demokrasi telah membuka arus informasi yang cepat dan beragam sehingga kepatuhan dapat dibentuk "tanpa paksaan" dengan cara membentuk "wacana bersama".
Namun, suksesnya karantina telah menimbulkan masalah kultural yang tak kalah besar. Hilangnya aktivitas di ruang publik serta berhentinya pabrik-pabrik telah menurunkan produksi kultural dan ekonomi yang, dalam skala besar, telah memperlambat percepatan sejarah serta perkembangan peradaban.
Di masa normal, percepatan informasi dan produksi kultural lainnya dilakukan dalam rangka mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan populasi, dengan implikasi berupa tingkat stres masyarakat dalam mengelola volume, trafik, dan variasi pengetahuan yang tinggi. Di masa krisis corona, tingkat stres masyarakat justru timbul akibat perlambatan arus informasi serta berkurangnya volume dan variasi pengetahuan yang diterima, diproduksi, dan didistribusikan.
Masalah psikologis tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan problem sosial yang lebih elementer seperti bertambahnya tingkat dan jumlah penduduk miskin akibat penurunan produksi ekonomi yang drastis, kesulitan akses terhadap bahan pangan pokok bagi masyarakat tertentu sebagaimana di ruang hunian yang tumpang tindih baik etnis, agama, kelas ekonomi seperti di perkotaan serta daerah-daerah terpencil.
Perlambatan di berbagai bidang baik ekonomi, kultural, dan mental tersebut merupakan arus balik yang ekstrem dari realitas normal yang mengacu pada perlunya percepatan demi mencapai kemajuan. Pembalikan tersebut akan terasa berat mengingat kekayaan kultural yang begitu besar dan beragam harus diubah ritme dan orientasinya dalam waktu yang cepat. Akibatnya terjadi keterkejutan, peningkatan tekanan, serta banyaknya pengetahuan kultural yang kurang relevan karena harus diadaptasi ulang. Jika terus dipaksakan untuk melaju dengan cepat, akan terjadi ketidakkoherenan dengan realitas hidup yang sedang melambat.
Dalam proses tersebut, kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan keadaan amat menentukan ketahanan mereka di tengah wabah, baik terkait ketepatan dalam memilah dan memilih pengetahuan dari pengalaman, fleksibilitas dalam mengubah orientasi ruang dan waktu, peralihan pola hidup dan pengolahan makanan, serta dalam penyederhanaan nilai-nilai serta praktik-praktik kultural yang kompleks agar menjadi lebih praktis.
Di samping itu, daya lenting suatu masyarakat juga patut diperhitungkan, di mana semakin kuat sebuah tekanan justru akan menimbulkan daya dorong besar. Hal tersebut amat dibutuhkan dalam menghadapi krisis serta penataan kehidupan kembali setelah masa pandemi berakhir.
Faisal Kamandobat penyair dan peneliti di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia (AWCPH-UI), Jakarta