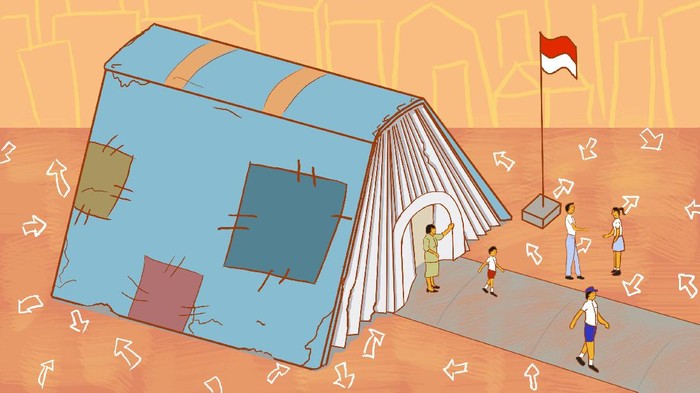Ia tertarik mengikuti lomba itu. Hadiahnya terhitung besar pada masa itu, Rp 750.000,00. Dalam perjalanan pulang ke Madiun, Pak Sartono menggumamkan dan menyiulkan nada-nada yang nantinya ia tuliskan. Namun, hingga tiba di rumah, ia sama sekali tak mendapat ide untuk menulis liriknya.
Saat hendak menyelesaikan lagu itu, tenggat waktu yang ditetapkan panitia lomba tinggal dua minggu. Dengan bantuan istrinya, yang mengisahkan kehidupan Suroyo yang dikenal baik oleh mereka berdua, dan kadang dipanggil Pak Royo, lagu itu pun selesai. Damiati, istri Sartono, bercerita tentang Pak Royo yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena musibah yang menimpa keluarganya. Ia sampai mengamen karenanya, sambil tetap mengajar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah lagu selesai ditulis, persoalan terakhir datang. Ketika hendak mengirimkan lagu itu ke Jakarta, Pak Sartono tidak memiliki cukup uang. Ia pun pergi ke toko yang menerima lungsuran pakaian bekas, menjual pakaiannya. Uangnya dipakai untuk membeli prangko.
Perubahan Lirik
"Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" menjadi juara, ditetapkan menjadi "Himne Guru". Kalau Anda memerhatikan lirik lagu itu, ada yang berubah di bagian akhir. Dua baris lirik di bagian akhir, versi awalnya begini:
Engkau patriot pahlawan bangsa
Tanpa tanda jasa
Tapi, kemudian versi barunya menjadi:
Engkau patriot pahlawan bangsa
Pembangun insan cendekia
Kalau Anda mendengarkan versi barunya dan membandingkan dengan versi lama, kata 'tanpa' jadi 'pembangun', pengubahan dilakukan dengan menambahkan not (karena ada penambahan satu suku kata); kata 'tanda' jadi 'insan' (tetap dua suku kata); kata 'jasa' yang di versi awal agak melantun dan dituangkan dalam tiga not, diganti 'cendekia'.
Waktu saya berkunjung ke rumah Pak Sartono di Madiun pada 14 Januari 2012, perubahan lirik lagu itu sempat saya tanyakan. Di rumah Pak Sartono yang sederhana, di ujung Jalan Halmahera, Madiun saya mengobrol akrab dengan Pak Sartono dan Bu Damiati. Kami mengobrol hampir tiga jam; mereka menyambut saya seperti teman lama.
Dari obrolan itu saya pun tahu, perubahan itu ternyata bukan inisiatif Pak Sartono, tapi pemerintah. Di Harian Kompas, 24 November 2008 juga disebutkan bahwa perubahan tersebut merupakan hasil negosiasi antara Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, PGRI, dan Pak Sartono.
Sejak "Himne Guru" mulai sering berkumandang di Tanah Air pada 1980-an, guru di Indonesia menyandang gelar "pahlawan tanpa tanda jasa", sesuai judul awal lagu ciptaan Sartono hasil lomba tersebut. Ketiadaan tanda jasa mewujud dalam profesi guru yang kurang sejahtera, seperti yang tampak juga pada lagu "Oemar Bakri" karya Iwan Fals.
Perubahan Nasib
Guru-guru sekarang sudah sejahtera dengan adanya sertifikasi; nasib mereka lebih diperhatikan pemerintah. Jasa guru mulai dihargai, walaupun tidak sedikit guru honorer yang hidupnya sederhana dan pas-pasan. Anak-anak muda tidak sedikit yang kini ingin menjadi guru. Guru diharapkan membangun manusia-manusia cendekia di seantero nusantara, bukan sosok yang jasanya tak dikenang atau diberi tanda.
Namun, kesejahteraan perlu diraih dengan cara-cara yang sesuai aturan. Dan, kesejahteraan itu pun menjadi pertanyaan bagi kompetensi guru: sudahkah ia menjadi guru yang profesional? Apakah tunjangan sertifikasi pada akhirnya hanya membuat guru lupa akan pentingnya sebuah pengabdian?
P. Swantoro dalam buku Dari Buku ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu (2002) menyatakan bahwa beberapa ilmuwan yang ada di Indonesia lahir karena bagi mereka, "hidup ini tidak ditentukan oleh nasi." Di buku itu ia juga menceritakan beberapa orang yang hampir abai terhadap uang, mempelajari ilmu dengan ketekunan yang tinggi, hingga ilmu menjadi sebuah jalan lain untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Kurang lebih seperti itulah bentuk dedikasi guru pada masa lalu.
Tidak sedikit laporan yang menyebutkan bahwa kinerja guru yang disertifikasi tidak mengalami peningkatan siginifikan.Ada juga berita di internet tentang banyaknya ketidakjujuran yang dilakukan guru dalam proses pengajuan sertifikasi. Tentu, perlu ada pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, perubahan nasib dan kesejahteraan adalah impian banyak orang, begitu juga guru. Kiranya, lewat perjuangan hidup Pak Sartono, pembaca sekalian—terutama para guru—tetap bersemangat menjadi terang bagi negeri ini: tetap menjadi "pelita dalam kegelapan", selalu menjadi "embun penyejuk dalam kehausan"; sehingga dengan cara demikian, "namamu akan selalu hidup dalam sanubari" anak-anak negeri.
Selamat Hari Pendidikan Nasional!
Sidik Nugroho guru, pemerhati masalah sosial (mmu/mmu)