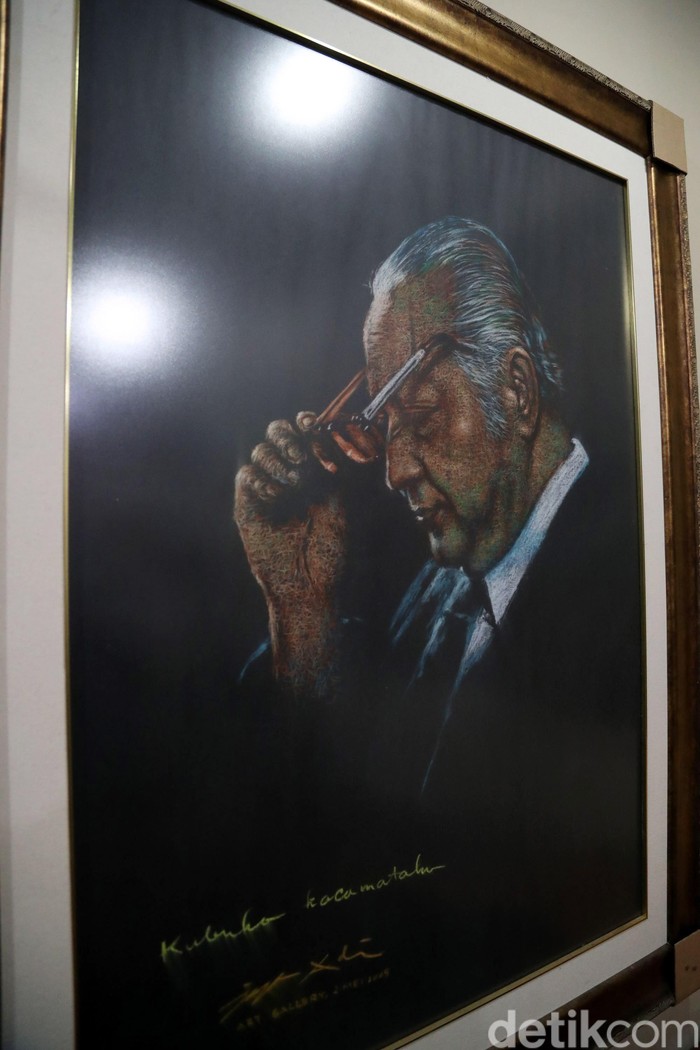Bagaimana sebenarnya lapangan kerja di era Jokowi kini? Apakah era Soeharto lebih baik dalam hal ketersediaan lapangan kerja?
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menjelaskan gambaran umum era Jokowi. Ada lima hal yang dia kemukakan sebagai bukti bahwa era Jokowi lebih baik dalam ketersediaan lapangan kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sementara itu, pada era dulu sektor ekonomi masih relatif terbatas. Pada 1986, misalnya, sekitar 54% tenaga kerja di Indonesia bergerak pada sekor pertanian," kata Erani kepada detikcom, Kamis (29/11/2018).
 Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika. (Rachman Haryanto/detikcom) Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika. (Rachman Haryanto/detikcom) |
Hal kedua yang disampaikan sebagai bukti ketersediaan lapangan kerja era Jokowi sudah lebih baik ketimbang era Soeharto, adalah soal perbaikan kualitas penyerapan tenaga kerja. Kualitas dalam hal ini adalah tingkat pendidikan tenaga kerja.
Data BPS menjadi rujukan Erani. Pada 1986 jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah mencapai 83% dari 62,45 juta orang, terdiri dari 22% tidak sekolah, 34,4% tak tamat SD, dan 27,1% tamat SD. Sedangkan di era Jokowi, yakni Agustus 2018, tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah tinggal 40,68% atau separuhnya dari era Orde Baru 1986.
Hal ketiga yakni soal jumlah pengangguran. Jokowi dinyatakannya mampu menyediakan lapangan kerja untuk lulusan baru. Sepanjang 2015-2018, jumlah angkatan kerja rata-rata naik 1,83% per tahun. Jumlah pengangguran rata-rata turun 0,75% per tahun.
"Data ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu menurunkan angka pengangguran di tengah kenaikan angkatan kerja," kata Erani.
Hal keempat adalah soal partisipasi angkatan kerja, yakni rasio jumlah angkatan kerja dibanding dibandingkan jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah indikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah.
"Pada era Soeharto angkanya bergerak pada 66%, sedangkan sekarang sudah di atas 67%, bahkan sempat mencapai 69% pada Februari 2017," kata Erani.
Hal keempat adalah kesejahteraan tenaga kerja, indikatornya adalah tingkat inflasi. "Pada era sekarang rata-rata inflasi di bawah 4% per tahun; sedangkan pada masa dulu inflasi pernah sangat tinggi, seperti pada 1972-1974 rata-rata di atas 25%," kata Erani.
 Jakarta tahun 1960-an (Pool) Jakarta tahun 1960-an (Pool) |
Kembali ke soal kuli sindang. Mereka adalah buruh kasar yang berasal dari sektor pertanian, kebanyakan tunakisma (tak memiliki lahan). Berbekal kemampuan mencangkul, mereka pergi ke Jakarta berharap mendapat secuil kue pembangunan.
Baca juga: Flashback Ekonomi di Zaman Orde Baru |
Soal tingkat pendidikan, kebanyakan kuli sindang hanya berpendidikan rendah. Misalnya Udin (40), kuli sindang yang sering nongkrong di seberang Stasiun Grogol, Jakarta Barat. Dia berharap perhatian pemerintah. "Inginnya sih lebih diperhatikan. Kita kan pekerja kasar nih, inginnya ada lapangan kerja yang bagus, jangan cuma untuk yang berpendidikan saja, tapi seperti kita yang cuma lulusan SD, juga diperhatikan," ujar Udin.
 Kuli-kuli sindang nongkrong menunggu tawaran kerja di TMP Kalibata. (Adhi Indra Prasetya/detikcom) Kuli-kuli sindang nongkrong menunggu tawaran kerja di TMP Kalibata. (Adhi Indra Prasetya/detikcom) |
Sepengamatan detikcom, kuli-kuli sindang di kawasan Grogol maupun di TMP Kalibata didominasi oleh pria-pria yang tak lagi muda, paling tidak di atas 35 tahun. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan kerja di era sekarang. Saking sulitnya, kuli usia nyaris kepala tujuh bernama Jarmin menyarankan agar anak dan cucunya tak menjadi kuli Sindang.
"Sebagai orang tua, kita menganjurkan wiraswasta, jualan. Karena yang namanya kerja, sudah dialami kita sendiri, sampe umur segini, repot. Apalagi ke depan. Jadi kita menyarankan pada anak-anak seperti itu, dan pelaksanaannya juga sudah ada," kata Jarmin (69) saat diwawancarai detikcom di sekitar TMP Kalibata.
Dalam ranah ketenagakerjaan, kuli sindang tergolong sebagai pekerja sektor informal. Menurut keterangan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menghimpun data hingga Agustus 2018, sebanyak 70,49 juta orang (56,84% dari keseluruhan pekerja) menggantungkan hidupnya pada sektor informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal turun sebesar 0,19% poin dibanding Agustus 2017.
Bila menilik dari pengakuan mereka yang lebih banyak menganggur ketimbang bekerja dalam sepekan, maka mereka masuk juga ke kategori pekerja paruh waktu yang bekerja kurang dari 35 jam sepekan. Adapun dari semua pekerja, sebanyak 22,07% merupakan pekerja paruh waktu. Mereka juga masuk dalam pekerja bebas nonpertanian, karena bekerja pada orang lain secara tidak tetap.
Bila melihat penghasilan kuli bangunan yang tak menentu, mereka rentan masuk dalam golongan miskin. Sebagaimana diberitakan detikcom pada 30 Juli 2018 lalu, BPS menentukan garis kemiskinan berdasarkan pendapatan Rp 401.220 per kapita per bulan. Adapun garis kemiskinan Jakarta lebih tinggi, yakni Rp 593 108 per kapita per bulan, dan garis kemiskinan per rumah tangga di Jakarta adalah Rp 3,1 juta per bulan.
Soal pekerjaan yang dirasakan kuli sindang semakin sulit didapat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI, Andri Yansyah, menilai itu karena lahan kosong di Jakarta semakin sedikit. Otomatis pembangunan yang membutuhkan tenaga kuli informal seperti mereka juga berkurang, menjadi lebih sedikit dibanding dengan puluhan tahun silam, saat pembangunan masih gencar dilakukan.
"Ini lahan DKI saat kosong kemudian dilakukan pembangunan pekerjaannya banyak, tapi lama-lama habis sudah dibangun semua, ya tentu kini (pekerjaannya) tinggal sedikit," kata Andri.
 Peralatan kerja kuli sindang (Dok Istimewa) Peralatan kerja kuli sindang (Dok Istimewa) |
Karena lapangan pekerjaan berkembang ke arah yang lain, maka para pekerja harus meningkatkan kemampuannya agar bisa terserap di dunia kerja yang baru. "Apalagi nanti, berbicara masalah revolusi industri 4.0, pekerja kita saja kalau tidak meningkatkan kualitasnya lama-lama bisa tergantikan sama industri teknologi semua, robot semua. Harus itu (beradaptasi), nggak bisa lagi berdiam diri," tandas Andri.
Simak terus artikel-artikel lain tentang kuli sindang di detikcom.
Tonton juga 'Di Reuni 212, Habib Rizieq Tegaskan 2019 Ganti Presiden':